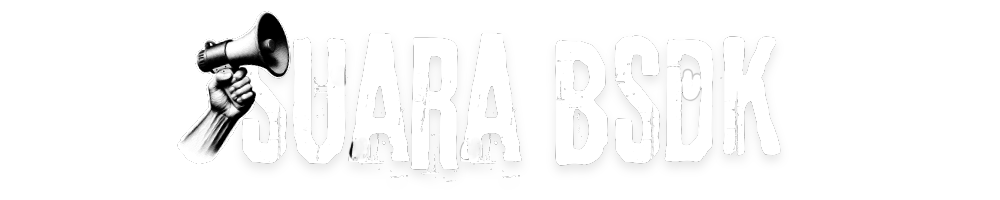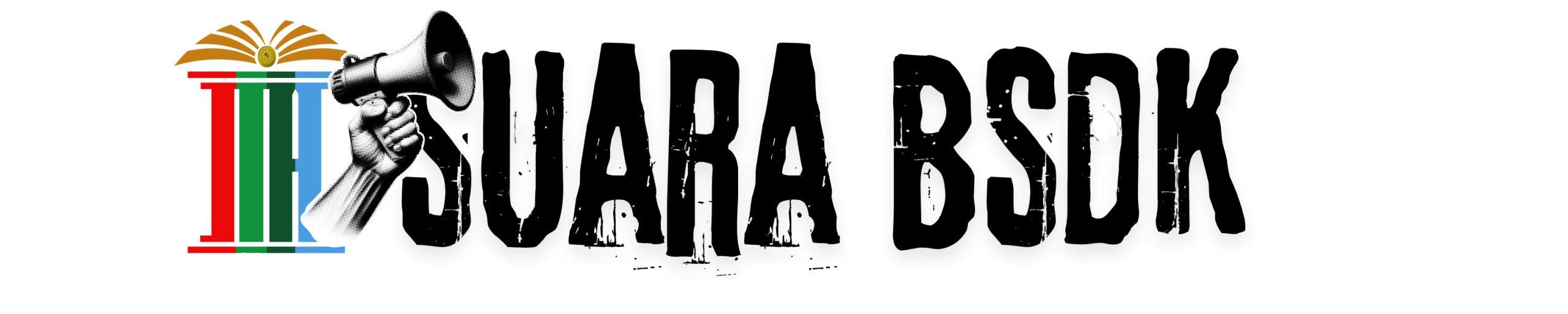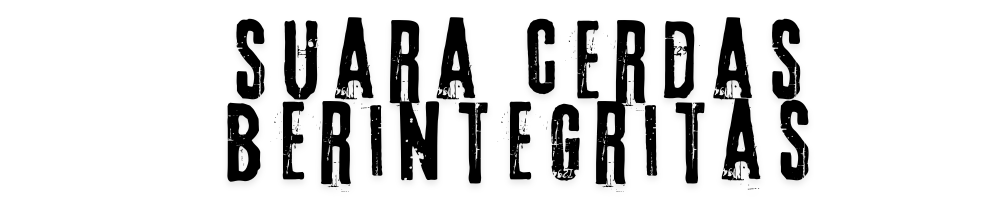Dilema Keadilan di Ruang Publik
Indonesia dan banyak negara lain telah menyaksikan sejumlah kasus hukum dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan konflik tajam antara keputusan pengadilan dan persepsi publik tentang keadilan. Tidak hanya ketidakcocokan pendapat, fenomena ini menunjukkan masalah struktural yang lebih dalam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia berkurang karena sering dianggap rentan terhadap korupsi dan intervensi. (Transparency International: 2025) Ketidakpuasan ini semakin diperparah ketika putusan hakim, meskipun didasarkan pada prosedur yang benar, terasa tidak adil di mata masyarakat.
Masyarakat tidak lagi pasif di era demokrasi dan keterbukaan informasi. Mereka dengan keras menuntut pertanggungjawaban dan keadilan yang jelas. Ruang digital berubah menjadi “pengadilan massa” di mana keadilan kolektif dipertimbangkan, seringkali sebelum atau bahkan bertentangan dengan keputusan pengadilan. Kondisi ini memaksa kita untuk merenungkan kembali, apakah doktrin hukum yang kaku dan otonom masih relevan di era di mana keadilan juga diukur dari penerimaan publik? Perdebatan ini menyentuh esensi hukum itu sendiri. Apakah hukum hanyalah sekumpulan aturan yang harus ditaati demi ketertiban, ataukah instrumen untuk mencapai keadilan? Sebagian besar sarjana hukum sepakat bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan.(Mahfud: 2014) Namun, ketika hukum terjebak dalam formalisme, ia berpotensi menjadi tujuan itu sendiri, mengabaikan realitas sosial dan penderitaan manusia yang ada di baliknya (Rahardjo: 2009, hlm 32-33).
Keadilan merupakan pilar utama membangun peradaban manusia yang harmonis (Rawls: 1999, hlm 3-5) namun konsepsinya tidak tunggal. Diskursus tentang keadilan seringkali terjebak dalam dikotomi yang membingungkan: antara keadilan hukum yang mengedepankan formalitas dan kepastian, dan keadilan masyarakat yang berakar pada sentimen, etika, dan nilai-nilai kolektif.(Nonet, Selznick: 1978, hlm 73) Distingsi fundamental antara dua konsep ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar di ruang publik, menimbulkan ketidakpuasan, krisis kepercayaan terhadap institusi hukum yang pada akhirnya, mengancam legitimasi negara hukum itu sendiri.(Rahardjo:2006, hlm 188-1990) Tulisan ini akan membahas perbedaan logis antara keadilan hukum dan keadilan masyarakat, menunjukkan betapa pentingnya menghubungkan keduanya untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan substantif.
Logika Keadilan Hukum: Formalisme dan Otonomi
Prinsip-prinsip formalitas, kepastian hukum, dan objektivitas membentuk dasar logika keadilan hukum. Ia bergantung pada bunyi pasal, prosedur standar, dan pembuktian. Menurut pandangan ini, keadilan dicapai melalui proses peradilan yang objektif dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menjaga kepastian hukum dan predictability (kemampuan untuk diprediksi) untuk mencegah kekacauan dalam masyarakat adalah prioritas utamanya..(Kelsen: 1967: hlm 201-205).
Hakim, dalam sistem ini, bertindak menerapkan hukum secara konsisten dan adil bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau opini publik. (Montesquieu: 1949, hlm 6) Dalam kasus pidana, contoh paling jelas menunjukkan bahwa terdakwa hanya dianggap bersalah jika bukti yang diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum, terlepas dari kebencian publik terhadapnya. Logika hukum mengutamakan keadilan prosedural dari pada perasaan kolektif dalam situasi seperti ini. Contoh lain dalam pengujian di Peradilan administrasi dimana pengujian terhadap keputusan maupun Tindakan administrasi didasarkan atas Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun tidak ada kriteria yag tersirat mengenai keadilan masyarakat sebagai representasi atas perasaan kolektif.
Prinsip kepastian hukum adalah dasar keadilan hukum. Putusan harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang diatur undang-undang. Sistem ini berpusat pada doktrin “dua alat bukti sah dan keyakinan hakim.” Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar yang kuat dan mencegah penghukuman sewenang-wenang. Hakim tidak dapat membuat keputusan mereka hanya berdasarkan rumor atau pendapat publik; mereka bergantung pada alat bukti dan prinsip pembuktian. Keadilan ini mengabaikan kebenaran materiil yang tidak dapat dibuktikan secara formal karena keterikatan mereka pada formalitas. Karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memenuhi standar hukum, seseorang yang dianggap bersalah secara moral dan sosial dapat dibebaskan. Ini menghasilkan keadilan prosedural yang kadang-kadang bertentangan dengan keadilan substantif.(Rahardjo: 2000 hlm 174-176).
Keadilan Masyarakat: Emosi, Konteks, dan Partisipasi
Berbeda dengan hukum, keadilan masyarakat tidak terikat oleh formalitas karena lahir dari rasa keadilan yang hidup dalam hati nurani kolektif. Keadilan masyarakat seringkali bersifat kontekstual, mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi, emosi, dan sejarah suatu kasus. Prioritas utamanya adalah keadilan substantif, yaitu hasil yang dirasakan benar dan adil oleh mayoritas masyarakat (Santos: 2002, hlm 458-460).
Keadilan ini menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial yang tidak selalu tercakup dalam hukum. Masyarakat merasa keadilan telah dicederai ketika seorang pelaku kejahatan diberi hukuman ringan karena adanya celah hukum. Keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi ditunjukkan dengan reaksi publik yang marah, demonstrasi, dan tuntutan untuk hukuman yang lebih berat. Dalam banyak kasus, keadilan masyarakat bahkan menuntut keadilan restoratif, yang melibatkan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi selain hukuman itu sendiri.(Zehr: 2015, hlm 28-32).
Rasa keadilan kolektif adalah dasar dari keadilan masyarakat. Bagi masyarakat umum, keadilan adalah ketika “pelaku yang jelas-jelas bersalah” menerima hukuman yang pantas. Ini tidak peduli bagaimana bukti diperoleh atau apakah proses hukumnya sudah dilakukan dengan benar. Bukti informal, seperti kesaksian dari mulut ke mulut, rekaman video yang beredar di media sosial, dan asumsi umum, seringkali menjadi sumber keyakinan. Logika ini rentan terhadap prasangka, perasaan, dan “hukum massa”; keadilan ini memiliki kelemahan tanpa batasan formal. Tekanan publik dapat membahayakan prinsip praduga tak bersalah, dan seseorang dapat dihukum secara sosial bahkan sebelum diadili (Citron dan Franks: 2014, hlm 345-391).
Tinjauan Terhadap Distingsi Keadilan
Distingsi fundamental antara kedua konsep ini menciptakan dilema.Saat logika hukum lebih mengutamakan kepastian hukum, ia berpotensi mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, jika keadilan hukum tunduk sepenuhnya pada kehendak publik, ia akan kehilangan objektivitas dan integritasnya, berpotensi menjadi “hukum massa” yang anarkis. (Selznick: 1969 hlm 41-43) Ketergantungan berlebihan pada formalisme hukum seringkali membuat proses peradilan terasa jauh dan tidak relevan bagi masyarakat. Bahasa hukum yang kaku dan prosedur yang berbelit-belit menciptakan jurang antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hukum, yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, justru dianggap sebagai entitas asing yang bekerja dengan logikanya sendiri, terlepas dari realitas sosial (Fuller: 1969, hlm 33-94).
Prioritas keadilan seringkali menjadi medan tarik-menarik antara prinsip-prinsip hukum yang kokoh dan tekanan populis. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seringkali dihakimi oleh “pengadilan opini publik” sebelum keputusan hukum resmi dikeluarkan. Ketika hasil persidangan tidak sesuai dengan harapan publik, legitimasi sistem hukum dipertanyakan. Ini menciptakan dilema bagi para penegak hukum: (Friedman:1975, hlm 16-21) Apakah mereka harus mengubah keputusan mereka untuk meredam kemarahan publik atau memprioritaskan prinsip hukum yang telah ditetapkan? Ini menunjukkan bahwa meskipun logika hukum mengklaim kesetaraan, namun dapat dipengaruhi oleh konflik kekuasaan ataupun faktor esternal non hukum lainnya.
Tantangan terbesar bagi setiap negara hukum adalah menciptakan harmoni antara logika keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Mencari titik temu yang konstruktif daripada menghapus salah satunya sebagai solusinya. Hukum harus dapat beradaptasi dan tidak sepenuhnya menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat. Para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil harus terus menerus berdialog satu sama lain.(Hubbermas: 1996, hlm 287-328) Pada akhirnya, prioritas tertinggi adalah keadilan yang berkeadilan. Ini adalah sebuah sintesis yang menggabungkan logika keadilan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan tidak hanya harus berlaku secara prosedural, tetapi juga harus dirasakan dan diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan adil. Tanpa pengakuan ini, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan kosong yang tidak memiliki legitimasi moral.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, perlu agar keadilan masyarakat menjadi parameter yang jelas bagi hakim. Tidak berarti bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan “voting” publik, sebaliknya berarti bahwa hakim harus diberikan lebih banyak ruang untuk mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari suatu kasus sehingga memungkinkan hakim untuk menafsirkan doktrin “dua alat bukti dan keyakinan hakim” secara lebih fleksibel, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif, di mana kesaksian korban yang konsisten dan meyakinkan dapat dianggap sebagai bukti yang kuat,(Baldissone: 2017, hlm 77-99).
Meningkatkan penerapan keadilan Restoratif: dalam kasus tertentu, hakim bisa mengarahkan penyelesaian kasus ke arah keadilan restoratif, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Hal ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mencapai keadilan yang lebih substantif (Zehr: 2015, hlm 28-32) Pada akhirnya, tantangannya adalah bagaimana menggabungkan rasionalitas dan formalitas hukum dengan empati dan moralitas sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah membangun sistem hukum yang adil untuk memangkas distingsi keadilan logika hukum dengan keadilan masyarakat. (Tyler: 2006, hlm 45-62).
Norma Jalan Tengah
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berarti bahwa hakim tidak boleh hanya menjadi “corong undang-undang” yang hanya menerapkan hukum secara kaku. Sebaliknya, mereka harus menjadi penafsir hukum yang proaktif, membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip dan keadaan masyarakat. Ini adalah pengakuan bahwa hukum formal tidak selalu mencakup semua aspek keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan pasal ini adalah untuk menjembatani perbedaan logika antara keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Meskipun sistem hukum memerlukan pembuktian yang didasarkan pada dua alat bukti sah dan keyakinan hakim, pasal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keadilan masyarakat tanpa tergantung pada pembuktian formal. Tujuannya adalah untuk menghindari putusan yang meskipun mereka sah secara prosedural tetapi tampak tidak adil bagi masyarakat umum, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Meskipun keadilan masyarakat tidak memiliki kriteria pembuktian yang sama dengan hukum, ini tidak berarti bahwa keadilan masyarakat tidak dapat divalidasi karenanya hakim harus memahami konteks sosial-ekonomi dan sejarah kasus. Contohnya dalam kasus sengketa tanah ataupun sengketa lingkungan hidup mereka harus memahami adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat yang mungkin tidak tercantum dalam peraturan maupun sertipikat, selain itu hakim dapat secara langsung mempelajari perspektif masyarakat melalui proses musyawarah atau mediasi, terutama dalam kasus yang memungkinkan keadilan restorative selain itu juga dapat mempertimbangkan secara mendalam amicus curiae maupun keterangan perwakilan komunitas masyarakat untuk didengar perspektif keadilannya. Tentu saja hal ini memerlukan pembaharuan atau setidaknya pemaknaan ulang terhadap hukum acara.
Membedakan keadilan masyarakat yang organik (alami) dengan keadilan masyarakat yang terkendali (digerakkan oleh pihak tertentu) adalah tantangan besar dalam mengidentifikasi keadilan masyarakat dewasa ini. Keadilan organik atau alami muncul secara spontan dari kesadaran kolektif masyarakat. Ini berasal dari empati dan solidaritas, contohnya seperti kemarahan publik atas kasus kekerasan terhadap anak ataupun perkara lingkungan hidup yang berdampak sangat besar bagi lingkungan dan generasi sedangkan keadilan masyarakat yang terkontrol, atau artifisial berarti adanya pihak-pihak tertentu, seperti kelompok kepentingan, menggunakan kampanye media sosial atau cerita yang disengaja untuk menciptakan keadilan yang dipersepsikan. Tujuannya adalah untuk memaksa hakim untuk membuat keputusan demi kepentingan tertentu, bukan demi keadilan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengancam integritas hukum dan prinsip objektivitas. Dalam situasi seperti ini, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara kontekstual mewajibkan hakim untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip keadilan yang alami atau organik, daripada tunduk pada pendapat publik yang dikontrol. Untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya, dengan menemukan cara untuk menggabungkan empati sosial dan rasionalitas hukum.
Penutup
Salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum khususnya sistem peradilan berasal dari distingsi antara logika keadilan hukum dengan keadilan masyarakat. Meskipun penting untuk stabilitas, logika hukum yang bergantung pada formalitas dan prosedur seringkali mengabaikan rasa keadilan substantif yang ada di masyarakat. Ketidaksesuaian ini menyebabkan krisis legitimasi, di mana keputusan pengadilan yang sah dianggap tidak adil secara moral dan sosial. Oleh karena itu, menjembatani perbedaan ini sangat penting. Memaksakan hukum untuk memenuhi keinginan publik bukanlah solusinya. Sebaliknya, solusinya adalah mendorong hukum yang lebih responsif atau fleksibel yang dapat disesuaikan dengan keadaan sosial.
Sebagai garda terdepan keadilan, hakim harus diberi kesempatan untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pada akhirnya, keadilan yang benar hanya dapat dicapai ketika sistem hukum juga mewakili moralitas masyarakat bukan tujuan itu sendiri yang terisolasi dari kenyataan, hukum harus kembali menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan.
Trisoko Sugeng Sulistyo
Hakim PTUN Surabaya
Mahasiwa PDIH Universitas Diponegoro
Sumber
Boaventura de Sousa Santos, “Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation,” 2nd ed. (London: Butterworths LexisNexis, 2002)
Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn,” Wake Forest Law Review 49 (2014)
Hans Kelsen, “Pure Theory of Law,” trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967)
Howard Zehr, “The Little Book of Restorative Justice,” revised and updated (New York: Good Books, 2015)
John Rawls, “A Theory of Justice,” revised edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999)
Jürgen Habermas, “Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy,” trans. William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1996)
Lawrence M. Friedman, “The Legal System: A Social Science Perspective,” (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
Lon L. Fuller, “The Morality of Law,” revised ed. (New Haven: Yale University Press, 1969)
Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia,” edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
Montesquieu, “The Spirit of Laws,” trans. Thomas Nugent (New York: Hafner, 1949), Book XI, Chapter 6.
Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
———————–, “Membedah Hukum Progresif” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
———————-, “Ilmu Hukum,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
Philippe Nonet and Philip Selznick, “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law” (New York: Harper & Row, 1978)
Philip Selznick, “Law, Society, and Industrial Justice,” (New York: Russell Sage Foundation, 1969),
Riccardo Baldissone, “Towards a Flexible Legal Hermeneutics,” Law and Critique 28, no. 1 (2017)
Transparency International, “Global Corruption Barometer: Asia 2020,” accessed September 18, 2025, https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020.
Tom R. Tyler, “Why People Obey the Law,” (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI