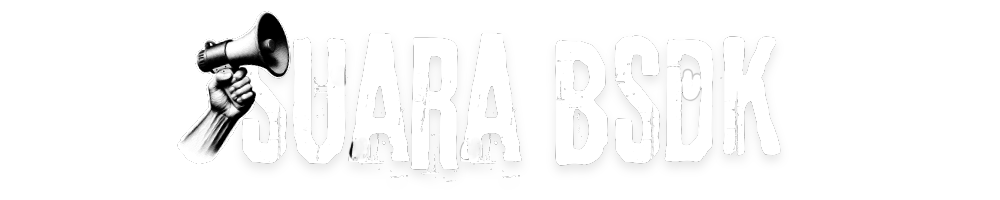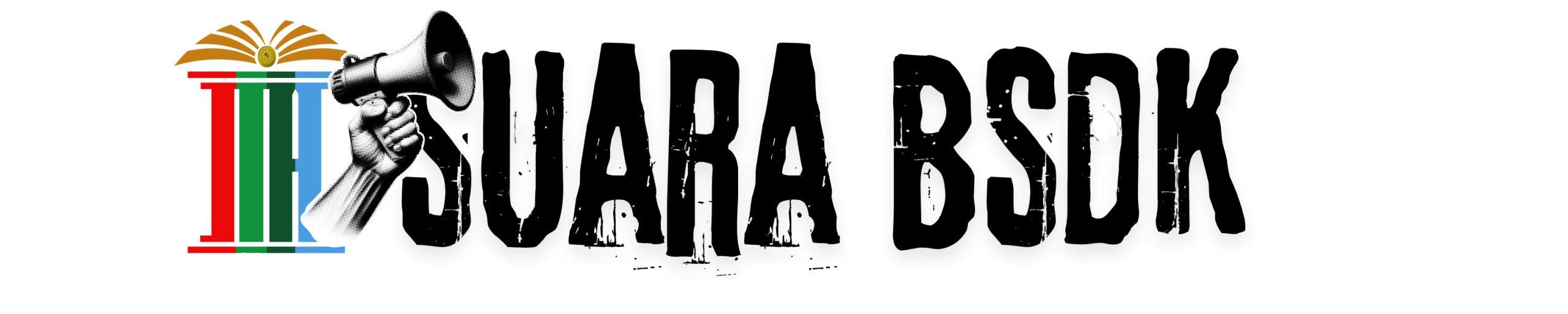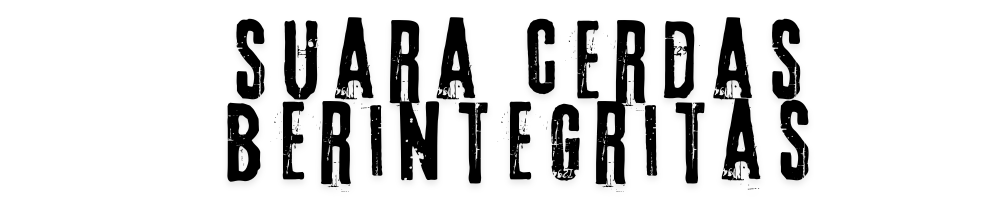1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian dan penegakan hukum pidana. Kejahatan modern seperti kejahatan siber, korupsi lintas negara, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan memerlukan pemahaman ilmiah yang melampaui teks undang-undang.
Oleh karena itu, dalam paradigma hukum kontemporer, hakim tidak lagi cukup hanya berperan sebagai “interpreter of law”, yakni penafsir aturan hukum positif, tetapi juga harus menjadi “interpreter of science”, yakni penafsir terhadap fakta-fakta ilmiah yang muncul dalam proses pembuktian. Sebab, hukum tidak hidup dalam ruang hampa; ia selalu berinteraksi dengan temuan dan metode ilmiah yang berkembang di masyarakat[1].
2. Hakim sebagai Interpreter of Law
Secara tradisional, hakim dipandang sebagai pelaksana undang-undang (la bouche de la loi) sebagaimana ajaran Montesquieu dalam L’esprit des Lois. Hakim hanya menafsirkan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif, tanpa menambahkan atau mengurangi maknanya.
Dalam sistem hukum pidana klasik, pendekatan ini dikenal sebagai positivisme yuridis, di mana putusan harus didasarkan secara ketat pada ketentuan hukum tertulis. Menurut Hans Kelsen, tugas hakim hanyalah menurunkan norma umum (undang-undang) menjadi norma individual (putusan), tanpa memasukkan penilaian moral atau ilmiah[2].
Namun, dalam realitas modern, pendekatan ini menjadi tidak memadai. Fakta-fakta ilmiah seperti bukti DNA, rekaman digital, analisis forensik, dan data elektronik memerlukan kemampuan analisis lintas-disiplin yang tidak tercantum eksplisit dalam peraturan hukum.
3. Pergeseran Menuju Hakim sebagai Interpreter of Science
Paradigma baru peradilan menempatkan hakim bukan sekadar pelaksana teks hukum, melainkan sebagai penafsir realitas ilmiah yang menjadi dasar bagi penerapan hukum secara adil.
Hakim sebagai interpreter of science berarti hakim harus mampu:
- Memahami dan menilai bukti ilmiah — seperti hasil laboratorium forensik, audit digital, atau uji balistik;
- Menilai validitas ilmiah suatu metode — misalnya chain of custody dalam bukti elektronik;
- Menimbang keterangan ahli secara epistemologis, bukan sekadar formalitas;
- Menghubungkan antara norma hukum dan teori ilmiah, agar putusan berdasar pada scientific truth dan bukan hanya legal truth.
Menurut Satjipto Rahardjo, hakim modern tidak hanya menegakkan hukum secara formal (law in books), tetapi juga menegakkan “hukum yang hidup” (living law) dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ilmiah di mana hukum itu bekerja[3].
4. Hakim dalam Perspektif Ilmu dan Pembuktian
Perkara pidana modern menuntut hakim memiliki literasi ilmiah karena proses pembuktian tidak hanya melibatkan fakta hukum, tetapi juga fakta ilmiah. Misalnya:
- Dalam perkara pembunuhan, pembuktian sering bergantung pada DNA analysis atau time of death estimation.
- Dalam perkara korupsi dan keuangan, diperlukan forensik akuntansi dan audit digital.
- Dalam perkara lingkungan, hakim harus memahami bukti ilmiah mengenai pencemaran.
Dengan demikian, hakim berperan ganda: sebagai ilmuwan yang menafsirkan fakta ilmiah (scientific interpreter) dan sebagai yurist yang menegakkan norma hukum (legal interpreter).
Lawrence Friedman menyebut bahwa fungsi hakim di era modern adalah mengintegrasikan legal reasoning dengan scientific reasoning untuk menghasilkan keadilan yang empiris dan rasional[4].
5. Konsekuensi Epistemologis dan Etis
Peran hakim sebagai interpreter of science membawa dua konsekuensi besar:
a. Konsekuensi Epistemologis
Hakim harus memahami logika ilmiah (scientific logic) dalam menilai bukti. Artinya, kebenaran hukum tidak lagi hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedural, tetapi oleh validitas ilmiah dari fakta yang terbukti di persidangan.
b. Konsekuensi Etis
Hakim dituntut menjaga integritas dalam menilai fakta ilmiah secara objektif, tanpa bias politik atau tekanan institusional. Hakim harus menjembatani dunia hukum dan dunia ilmu pengetahuan tanpa kehilangan orientasi moral keadilan (ius et scientia).
6. Implementasi dalam Hukum Indonesia
Dalam konteks hukum Indonesia, peran hakim sebagai interpreter of science mulai tampak dalam beberapa kasus penting, antara lain:
- Kasus Forensik DNA dalam perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin (2016) — Hakim mengintegrasikan hasil laboratorium ilmiah sebagai dasar penentuan kesengajaan.
- Kasus Lingkungan PT Lapindo Brantas — Hakim mempertimbangkan hasil penelitian geologi dan seismologi sebagai bukti ilmiah.
- Perkara Tipikor berbasis digital evidence — Hakim menilai log data, email forensik, dan metadata sebagai alat bukti sah menurut hukum acara.
Hal ini menunjukkan bahwa hakim kini tidak dapat menghindar dari tanggung jawab epistemologis sebagai penafsir ilmu pengetahuan.
7. Kesimpulan
Hakim modern bukan lagi hanya interpreter of law yang berorientasi pada teks, melainkan juga interpreter of science yang berorientasi pada realitas empiris dan pengetahuan ilmiah. Keberanian untuk menafsirkan hukum melalui kacamata ilmu pengetahuan menjadi kunci agar peradilan pidana tidak tertinggal oleh dinamika masyarakat ilmiah.
Dengan demikian, kebenaran hukum (legal truth) harus bersinergi dengan kebenaran ilmiah (scientific truth) agar putusan hakim bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara rasional dan adil secara substantif.
Daftar Pustaka
Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Friedman, Lawrence M. Law and Society: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Muladi. Hakim dan Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana Modern. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2008.
[1] Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 112.
[2] Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 273
[3] Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 65.
[4] Friedman, Lawrence M. Law and Society: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987, hlm. 78.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI