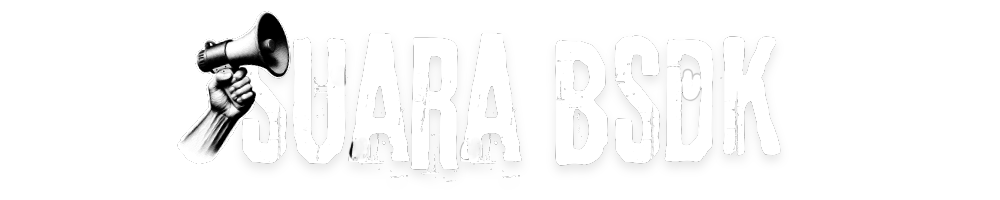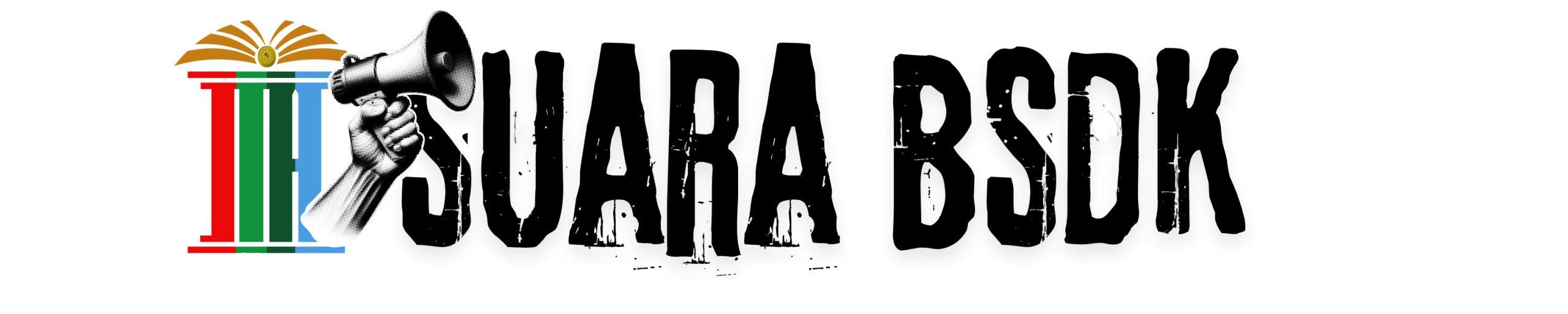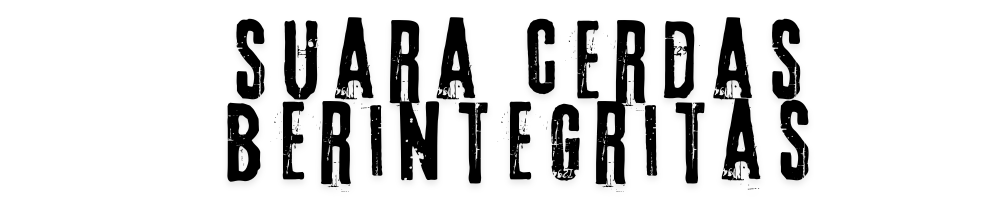Sejarah umat manusia selalu ditandai oleh relasi antara manusia dan alam. Peradaban besar lahir dari sungai, lembah subur, hutan, dan lautan yang melimpah. Namun, dalam dua abad terakhir, perkembangan teknologi dan keserakahan ekonomi telah melahirkan sebuah paradoks: di satu sisi, manusia berhasil menciptakan kemajuan material yang luar biasa, namun di sisi lain, kita tengah menggali kubur bagi kelangsungan hidup kita sendiri.
Hari ini, dunia menghadapi ancaman yang tidak kalah serius dari perang atau terorisme: kejahatan ekologis. Ia hadir dalam berbagai wajah, pembakaran hutan tropis yang menghasilkan kabut asap lintas negara, pencemaran laut akibat tumpahan minyak atau limbah plastik, perusakan terumbu karang oleh praktik penangkapan ikan illegal, hingga penggusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka. Semua tindakan itu bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan bentuk agresi terhadap kehidupan itu sendiri.
Para ilmuwan iklim memperingatkan bahwa kita memasuki era Anthropocene, masa ketika aktifitas manusia menjadi kekuatan geologis utama yang mengubah bumi. Namun peringatan ini sering tenggelam dalam hiruk pikuk politik jangka pendek dan hasrat mengejar keuntungan. Di tengah kebisuan itu, siapa yang akan berbicara bagi bumi?
Jawabannya ada pada mereka yang diberi mandat untuk menegakkan keadilan: para hakim. Hakim lebih dari sekadar penegak hukum. Hakim bukan hanya “mesin hukum” yang membaca teks undang-undang, melainkan penafsir moral yang harus berani berpihak pada kebenaran substantif.
Hans Jonas, dalam karyanya The Imperative of Responsibility, menekankan pentingnya etika tanggung jawab, bahwa manusia modern wajib bertindak dengan kesadaran penuh akan konsekuensi jangka panjang bagi generasi mendatang. Pandangan ini relevan bagi hakim lingkungan, karena dalam setiap putusan yang dijatuhkan bukan hanya berdampak pada hari ini, tetapi menentukan nasib bumi ratusan tahun ke depan. Dalam konteks kejahatan ekologis, hakim memiliki peran ganda. Pertama, sebagai penjaga supremasi hukum, hakim wajib memastikan bahwa setiap pelaku yang merusak lingkungan diproses secara adil dan transparan. Kedua, sebagai pelindung generasi mendatang, hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara visioner, melampaui kepentingan jangka pendek, dengan meletakkan kelestarian bumi sebagai prioritas utama.
Solidaritas Global: Mengikat Keadilan Ekologis
Kejahatan ekologis tidak mengenal batas negara. Asap kebakaran hutan di Kalimantan bisa menutupi langit Singapura dan Malaysia. Limbah industri yang dibuang ke sungai internasional dapat mencemari negara tetangga. Bahkan plastik sekali pakai yang kita buang hari ini bisa berlayar ribuan kilometer sebelum akhirnya terdampar di pantai negara lain.
Kondisi ini menuntut solidaritas yudisial global. Para hakim di seluruh dunia harus membangun kesepahaman bersama bahwa keadilan ekologis adalah kepentingan universal, bukan isu lokal. Solidaritas itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk:
Yang pertama, jaringan yudisial internasional yang memungkinkan hakim dari berbagai negara saling bertukar pengalaman, menciptakan landmark decision, dan metode penegakan hukum lingkungan.
Kedua, penguatan prinsip keadilan intergenerasional, kesadaran bahwa bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan generasi saat ini saja, melainkan titipan yang harus diserahkan utuh kepada generasi mendatang. Gagasan ini ditegaskan dalam Our Common Future (1987), laporan Brundtland yang melahirkan konsep sustainable development.
Ketiga, pengembangan doktrin hukum ekologis global, yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai hak asasi fundamental. Prinsip ini sudah diakui dalam berbagai instrumen internasional:
- Stockholm Declaration 1972, yang pertama kali menegaskan hak atas lingkungan hidup yang layak sebagai hak dasar manusia,
- Rio Declaration 1992, yang melahirkan prinsip precautionary principle dan polluter pays principle sebagai fondasi hukum lingkungan global, dan
- Paris Agreement 2015, yang memperkuat komitmen negara-negara dunia untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C.
Keempat, keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses hukum, sebagaimana ditekankan Aarhus Convention 1998, yang mengakui hak masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh keadilan lingkungan.
Dengan merujuk pada instrumen internasional ini, para hakim memiliki dasar kuat untuk menafsirkan hukum nasional dengan perspektif ekologis yang lebih luas.
Menamai Musuh yang Sebenarnya: Menggugat Penjahat Ekologis
Krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini tidak terjadi begitu saja. Ia bukan sekadar akibat “kesalahan teknis” atau “dampak sampingan pembangunan”, melainkan hasil dari keputusan-keputusan sadar yang diambil oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan ekonomi. Karena itu, kita tidak boleh lagi menyebut mereka hanya sebagai “pelanggar hukum” atau “pihak yang lalai”.
Menyebut mereka sekadar pelanggar hukum adalah sebuah penyamaran yang menipu. Istilah itu terlalu steril, terlalu jinak, seolah-olah apa yang mereka lakukan hanyalah kesalahan administratif biasa. Padahal, yang mereka tinggalkan adalah jejak kehancuran: hutan yang habis terbakar, sungai yang mati beracun, udara yang penuh asap, dan generasi yang kehilangan masa depan. Kata “pelanggaran” terlalu dingin, terlalu hambar, tak mampu menampung kedahsyatan kejahatan yang merobek jantung bumi.
Menyebut mereka hanya melanggar aturan sama saja dengan menyebut pembakaran rumah sebagai sekadar “pelanggaran tata tertib”—sebuah eufemisme yang melemahkan bobot moral dari kejahatan yang sesungguhnya. Mereka bukan sekadar pelanggar, mereka adalah penjahat ekologis yang harus dipanggil dengan nama sebenarnya, agar hukum dan nurani tidak terus dibutakan oleh bahasa yang menipu.
Kita harus berani menyebut mereka sebagai penjahat ekologis. Istilah ini penting, bukan hanya secara retorika, tetapi juga secara moral. Ia memberi bobot etik yang jauh lebih besar, setara dengan kejahatan-kejahatan serius lain dalam hukum internasional. Seperti halnya kita mengenali pelaku genosida atau kejahatan perang sebagai kriminal yang harus diadili, begitu pula mereka yang secara sistematis menghancurkan hutan, meracuni sungai, atau merampas tanah masyarakat adat harus dilihat sebagai penjahat terhadap kehidupan itu sendiri.
Bayangkan seorang pengusaha yang memerintahkan pembakaran lahan gambut, lalu asapnya membunuh ribuan orang dan merusak kesehatan jutaan anak. Atau sebuah korporasi yang membuang limbah beracun ke sungai, menghancurkan mata pencaharian nelayan, dan meninggalkan warisan penyakit bagi generasi mendatang. Atau aparat yang bersekongkol merampas tanah adat dengan kekerasan, menghilangkan hutan yang selama ratusan tahun menjadi penjaga ekosistem. Mereka ini bukan sekadar “aktor ekonomi” yang “melanggar peraturan”. Mereka adalah kriminal ekologis yang tindakannya melintasi ruang dan waktu—dampaknya dirasakan bukan hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Dalam The Natural Contract, Michel Serres mengingatkan bahwa manusia harus menandatangani kontrak baru dengan alam: sebuah kesepakatan moral untuk menghentikan dominasi eksploitatif, dan menggantinya dengan hubungan saling menghormati. Kontrak ini bukanlah sekadar dokumen hukum, melainkan sebuah kesadaran kolektif bahwa bumi bukan milik satu generasi saja. Dengan menamai pelaku perusakan lingkungan sebagai penjahat ekologis, hakim sesungguhnya sedang ikut menegakkan kontrak moral itu.
Lebih dari itu, penggunaan istilah penjahat ekologis dapat mengubah cara pandang masyarakat dan hukum. Ia membuka ruang bagi lahirnya kategori kejahatan baru, seperti yang kini mulai dibicarakan di forum internasional: ecocide atau kejahatan ekosida. Jika kejahatan terhadap kemanusiaan diadili di pengadilan internasional, mengapa kejahatan terhadap bumi—rumah kita bersama—tidak?
Karena itu, hakim tidak boleh lagi terjebak pada bahasa hukum yang steril dan netral. Bahasa punya kuasa: ia bisa melemahkan, tapi juga bisa meneguhkan keberanian. Dengan menyebut para perusak bumi sebagai penjahat ekologis, hakim sedang menegakkan bukan hanya pasal, tetapi juga nurani. Putusan yang berani menamai musuh dengan sebutan yang sebenarnya akan mengguncang kesadaran publik, memberi pesan bahwa hukum berpihak pada kehidupan, bukan pada kerakusan.
Hakim adalah penjaga terakhir kontrak moral antara manusia dan alam. Dengan pena yang ia gerakkan, ia bisa mengubah tafsir hukum menjadi perisai bumi. Jika hakim berani menyebut, mengadili, dan menghukum penjahat ekologis apa adanya, maka pengadilan bukan sekadar ruang formal, melainkan panggung sejarah—tempat di mana bumi akhirnya mendapatkan suaranya.
Putusan yang Menjadi Cahaya
Sejumlah putusan di berbagai belahan dunia telah menunjukkan arah baru. Di India, Mahkamah Agung menyatakan sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas hidup yang memiliki hak hukum. Sungai Gangga dan Yamuna adalah sungai suci bagi umat Hindu yang memiliki nilai spiritual, ekologis, dan juga sosial. Meskipun kemudian perkaranya dibawa lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, di tahun 2017 Pengadilan Tinggi Uttarakhand (Uttarakhand High Court) di India, mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan bahwa sungai Gangga dan Yamuna serta anak-anak sungainya adalah “entitas hidup” (legal persons) yang memiliki hak hukum seperti manusia. Sungai Gangga dan Yamuna diakui sebagai living entities (makhluk hidup secara hukum) yang memiliki status hukum seperti seorang manusia, dapat memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan hukum.
Di Kolombia pada tahun 2018, sejumlah anak muda Kolombia mengajukan gugatan konstitusi terhadap pemerintah karena gagal menghentikan deforestasi Amazon. Mereka berargumen bahwa kerusakan hutan Amazon mengancam hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat, kehidupan, kesehatan, serta keadilan antar-generasi. Data menunjukkan deforestasi Amazon meningkat tajam, terutama akibat ekspansi pertanian, peternakan, dan penebangan illegal. Putusan pengadilan menyatakan: Hutan Amazon di Kolombia adalah entitas yang memiliki hak hukum (subject of rights) bukan sekadar objek eksploitasi, sehingga Pemerintah Kolombia diperintahkan untuk: menyusun rencana aksi nasional dan lokal guna menghentikan deforestasi, melaksanakan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dan memastikan pelindungan Hutan Amazon demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Reasoning Pengadilan saat itu menggunakan prinsip keadilan antar-generasi, Hutan Amazon adalah “paru-paru dunia” yang memiliki peran penting dalam mengendalikan perubahan iklim global. Pelindungan Hutan Amazon bukan hanya isu nasional Kolombia, tetapi juga tanggung jawab internasional, sehingga hak generasi mendatang atas lingkungan sehat harus dilindungi.
Putusan ini memperkuat gerakan hukum internasional yang memberi hak-hak hukum pada alam dan menjadi preseden penting di Amerika Latin, menyusul putusan pengadilan sebelumnya yang mengakui Sungai Atrato (2016) sebagai subjek hukum yang menegaskan bahwa perubahan iklim dan deforestasi harus ditangani dengan pendekatan yudisial, bukan hanya eksekutif atau legislatif.
Di belahan dunia lain, pada tahun 2008 Ekuador melalui konstitusi mereka secara eksplisit mengakui “hak-hak alam” (rights of nature), menjadikan Ekuador pelopor dalam hukum ekologis global.
Kasus Vilcabamba River di tahun 2011, Pengadilan Ekuador memenangkan gugatan warga yang menuduh pemerintah merusak ekosistem sungai akibat proyek pembangunan jalan. Pengadilan menegaskan bahwa sungai memiliki hak untuk eksis dan dipulihkan. Putusan ini menjadi yurisprudensi pertama di dunia yang menegakkan hak-hak alam berdasarkan konstitusi. Ekuador memberi contoh nyata bahwa hak-hak alam dapat memiliki status hukum setara dengan hak asasi manusia. Menginspirasi negara lain, Bolivia dengan Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), putusan pengadilan di Kolombia (Amazon & Atrato River), serta gerakan rights of nature di berbagai belahan dunia.
Setiap putusan progresif adalah bukti bahwa hakim tidak hanya sekadar pelaksana hukum, tetapi juga agen perubahan. Mereka membentuk wajah baru hukum yang tidak lagi antroposentris, melainkan ekosentris.
Hukum untuk Alam, Hukum untuk Kehidupan
Bumi tidak memiliki pengacara. Sungai tidak bisa menulis laporan polisi. Hutan yang ditebangi tidak bisa hadir di ruang sidang sebagai saksi. Tetapi hakim bisa menghadirkan suara mereka. Hakim bisa menjadi perpanjangan lidah bagi alam yang bisu, bagi generasi mendatang yang belum lahir, dan bagi makhluk hidup lain yang tak mampu membela diri.
Seruan ini harus bergema: “Bersatulah para hakim sedunia melawan penjahat ekologis. Jadilah benteng terakhir bumi, bukan sekadar pelayan teks hukum”. Peran kita sebagai Hakim menjadi sangat strategis dalam menjaga warisan ekologis untuk masa depan. Kita memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat, dan ini menuntut visi jangka panjang dalam setiap putusan kita.
Seperti kata Mahatma Gandhi, “Bumi memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang.” Maka, keadilan ekologis bukan hanya untuk lingkungan, tetapi untuk semua kehidupan.
Karena tanpa keadilan untuk alam, manusia pun akan kehilangan hakikat keadilannya.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI