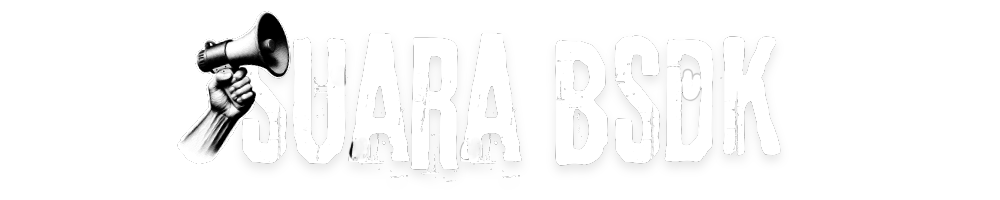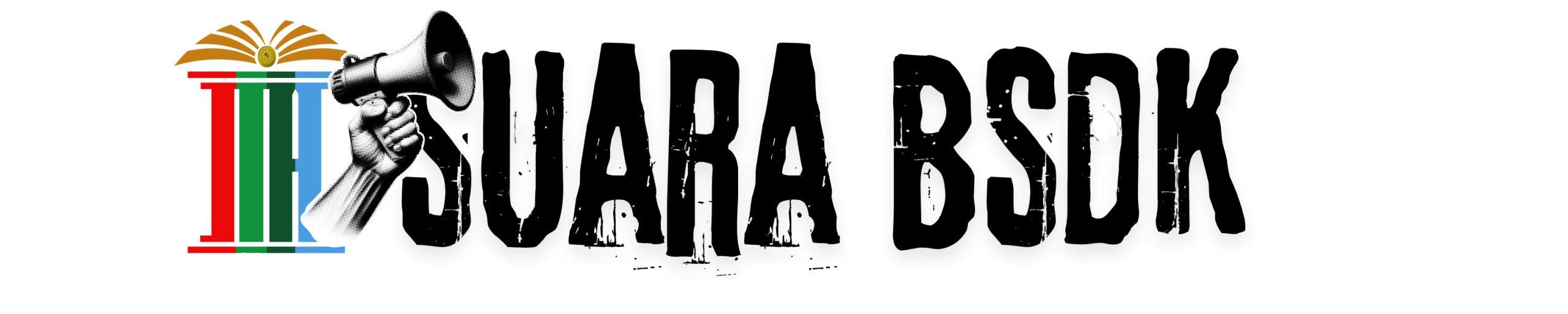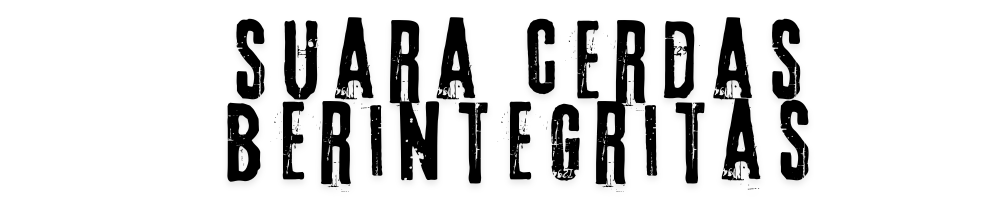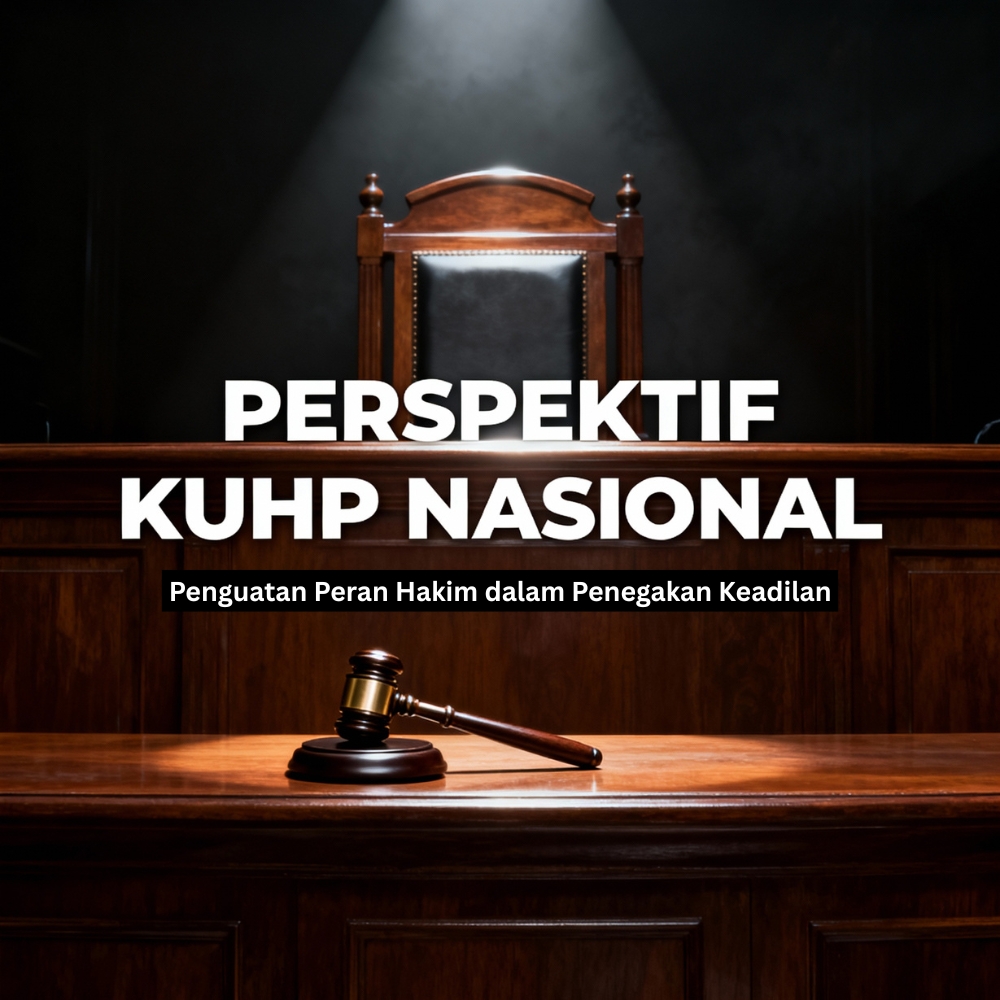Latar Belakang KUHP Nasional
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van straafrecht) tahun 1918 merupakan kodifikasi hukum materiel pidana warisan kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jis. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai produk colonial, KUHP mengadopsi nilai-nilai hukum Eropa yang saat ini dianggap banyak yang sudah tidak relevan dengan nilai dan tuntutan hukum masyarakat Indonesia.
Substansi KUHP merujuk pada aliran klasik (daad-straafrecht) yaitu sistem hukum pidana yang fokus pada tindakan atau perbuatan pidana dan sanksi apa yang diberikan pada pelaku. Sistem ini menekankan kecermatan Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasar serius tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, dalam perkembangannya, para sarjana mendorong implementasi aliran neo-klasik (daad-daader straafrecht) yang tidak hanya fokus pada tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga pada pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik turut mempertimbangkan situasi atau keadaan di dalam diri pelaku sebagai bagian dari pertimbangan menjatuhkan pidana.
Gagasan pembaruan hukum pidana nasional semakin menguat seiring adanya meningkatnya kesadaran akademisi dan praktisi hukum bahwa KUHP yang diberlakukan selama ini terlampau kaku dan tidak memberi ruang tafsir yang cukup bagi Hakim dalam memutus perkara. Apalagi, jika dikaitkan dengan konteks hukum dan budaya masyarakat Indonesia, muatan KUHP belum mengatur subjek hukum korporasi dan hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Di tengah tuntutan zaman dan semakin kompleksnya dinamika penegakan hukum pidana, para sarjana sepakat bahwa KUHP saat ini harus diubah dengan menerapkan sistem rekodifikasi terbuka dan terbatas.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI