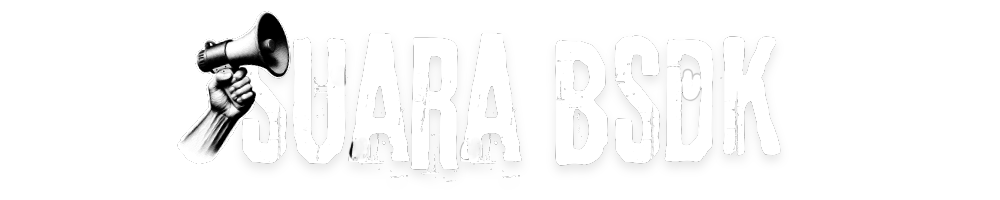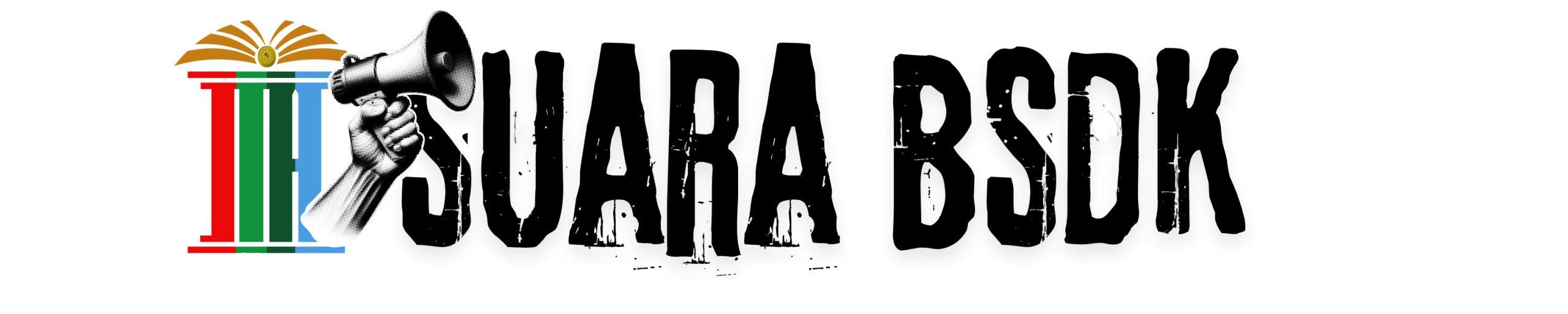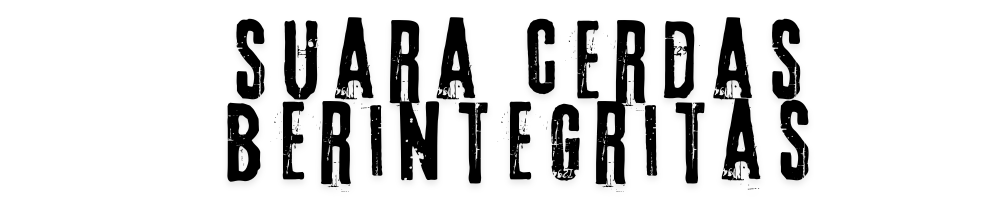Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp291,5 triliiun selama periode 2014-2023, dengan jumlah yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Sementara itu, Singapura berhasil mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, menempati peringkat 3 dalam Corruption Perception Index (CPI) tahun 2024 dengan skor 84, jauh melampaui Indonesia yang berada di peringkat 99 dengan skor 37.
Perbedaan tajam dalam tingkat korupsi antara kedua negara ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektifitas hukum dan kelembagaan pemberantasan korupsi. Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan luar biasa untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian.
Sebaliknya, Singapura mengandalkan satu lembaga tunggal, yaitu CPIB, yang memiliki independensi penuh dan beroperasi langsung di bawah kantor Perdana Menteri. Keberhasilan Singapura tidak terlepas dari penerapan Prevention of Corruption Act (PCA) yang ketat, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, sistem peradilan yang cepat dan efisien, serta budaya antikorupsi yang tertanam kuat dalam masyarakat.
Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri dalam konteks kerugian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensiial dalam tindak pidana korupsi. Konsep “dapat menimbulkan kerugian negara” yang bersifat delik formil telah menimbulkan perdebatan panjang, hingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mergubahnya menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara yang nyata dan dapat dibuktikan secara konkret. Lebih kompleks lagi, Indonesia mengenal konsep “merugikan perekonomian negara”, yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas namun menghadapi kendala dalam formulasi perhitungan dan lembaga mana yang berwenang melakukan penghitungan.
Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang kerugian negara. PCA tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi, melainkan lebih fokus pada tindakan pemberian suap (gratifikasi) sebagai imbalan atas tindakan tertentu. Pendekatan ini menyederhanakan proses pembuktian dan menghindari perdebatan teoretis mengenai perhitungan kerugian negara yang kerap menjadi hambatan dalam proses peradilan.
Perbedaan mendasar juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi. Indonesia menerapkan peradilan khusus melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tersebar di 34 provinsi, dengan komposisi majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Namun, perluasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke tingkat daerah menghadapi kendala sumber daya manusia dan kualitas hakim yang tidak biasa. Sementara itu, Singapura menangani kasus korupsi melalui sistem peradilan umum yang telah terintegrasi dengan baik, dengan dukungan penuh dari Attorney-General Chambers sebagai lembaga penuntut yang profesional dan independen.
Indonesia memiliki kerangka hukum antikorupsi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memperluas rumusan tindak pidana korupsi, memperberat ancaman pidana, memberikan kewenangan khusus kepada lembaga penegak hukum, dan mengenalkan mekanisme pembuktian progresif seperti pembalikan beban pembuktian.
Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok perbuatan, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dari 7 (tujuh) kelompok ini, yang terkait langsung dengan kerugian negara adalah kelompok pertama yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara kelompok lainnya tidak mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur delik.
Selain kerugian keuangan negara, Indonesia juga mengenal konsep kerugian perekonomian negara, yang memiliki ruang lingkup lebih luas, mencakup dampak ekonomi multidimensional, seperti kerugian ekologis, biaya pemeliharaan lingkungan, dan kerugian ekonomi akibat hilangnya kesempatan berusaha.
Definisi kerugian negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Definisi ini menekankan pada kerugian yang bersifat konkret dan terukur, berbeda dengan konsep “dapat merugikan” yang lebih luas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan dapat dibuktikan secara konkret.
Singapura mengatur tindak pidana korupsi terutama melalui Prevention of Corruption Act (PCA) yang disahkan pada 17 Juni 1960, yang merupakan undang-undang antikorupsi utama di negara tersebut. PCA memberdayakan CPIB dan mengatur definisi korupsi serta sanksi-sanksinya dengan cakupan yang luas, mencakup sektor publik maupun swasta. Berbeda dengan Indonesia yang memisahkan jenis korupsi berdasarkan delik yang dilakukan, Singapura lebih membedakan korupsi berdasarkan pelaku, yaitu apakah perbuatan korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat publik atau dilakukan oleh pegawai swasta.
Pasal 5 PCA mengatur larangan umum terhadap korupsi, yang melarang seseorang untuk secara korup meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima, atau memberikan, menjanjikan, atau menawarkan kepada orang lain suatu gratifikasi sebagai imbalan atau dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam hubungan dengan urusan atau transaksi apa pun. Konsep gratifikasi dalam PCA sangat luas, mencakup tidak hanya uang atau hadiah, tetapi juga pemberian dalam bentuk non-moneter seperti pinjaman, jabatan, pembebasan kewajiban, atau keuntungan lainnya.
Pasal 6 PCA mengatur secara khusus mengenai korupsi dalam hubungan agen-prinsipal, yang melarang agen untuk secara korup menerima atau mencoba memperoleh gratifikasi sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam urusan prinsipalnya, atau memberikan dokumen palsu yang dimaksudkan untuk menipu principal. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks sektor swasta, dimana PCA memperlakukan korupsi di sektor swasta dengan keseriusan yang sama dengan korupsi di sektor publik.
PCA tidak secara eksplisit mencantumkan persyaratan mengenai kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi. Fokus PCA adalah pada tindakan pemberian atau penerimaan gratifikasi yang bersifat korup, terlepas dan apakah tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial atau tidak. Pendekatan ini menyederhanakan proses pembuktian, karena penuntut tidak perlu membuktikan adanya kerugian konkret, cukup membuktikan bahwa telah terjadi pemberian atau penerimaan gratifikasi dengan niat korup.
Pasal 7 PCA mengatur larangan korupsi yang terkait dengan kontrak pemerintah atau lembaga publik, dengan sanksi yang lebih berat. Jika terbukti bahwa transaksi korup berkaitan dengan kontrak atau proposal kontrak dengan pemerintah, pelaku dapat dijatuhi denda hingga S$100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura) atau pidana penjara hingga 7 (tujuh) tahun, atau keduanya, untuk setiap dakwaan korupsi. Ini merupakan peningkatan dan sanksi umum yang hanya maksimal 5 (lima) tahun penjara.
Lebih lanjut dalam Pasal 8 PCA mengatur presumsi korup (presumption of corruption) untuk pegawai pemerintah atau lembaga publik. Jika pegawai pemeritnah menerima gratifikasi, maka gratifikasi tersebut dianggap diberikan atau diterima secara korup kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya. Ketentuan ini merupakan bentuk pembalikan beban pembuktian terbatas yang bertujuan menjaga inteegritas pelayanan publik. Pasal 20 lebih lanjut menyatakan bahwa pegawai publik yang menerima tawaran gratifikasi wajib melaporkannya dan menangkap pemberi gratifikasi. Kegagalan melakukan hal ini dapat dikenai denda hingga S$5.000,00 (lima ribu dolar Singapura) atau pidana penjara hingga 6 (enam) bulan.
Indonesia memiliki 3 (tiga) lembaga utama yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Singalura mengandalkan lembaga tunggal dalam pemberantasan korupsi, yaitu CPIB, yang didirikan pada September 1952, sebagai pengganti Anti-Corruption Branch dari Criminal Investigation Department. CPIB adalah lembaga independen yang beroperasi di bawah Kantor Perdana Menteri, dengan tugas memastikan tingkat otonomi dan ketidakberpihakan yang tinggi dalam investigasi.
CPIB memiliki kewenangan yang luas dalam investigasi korupsi, termasuk kewenangan untuk menangkap, menggeledah, menyita barang bukti, dan mewawancarai tersangka. Setelah investigasi selesai, CPIB menyerahkan hasil temuannya kepada Attorney-General’s Chambers (AGC) untuk memperoleh persetujuan Jaksa Penuntut Umum (Public Prosecutor) sebelum melanjutkan ke proses pengadilan. Sistem ini memastikan adanya pemisahan fungsi investigasi dan penuntutan yang jelas, sekaligus menjaga independensi dan objektifitas proses hukum.
CPIB juga aktif melakukan edukasi publik dan penjangkauan komunitas terkait antikorupsi, tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Program-program edukasi antikorupsi diintegrasikan sejak dini dalam sistem pendidikan, membentuk kesadaran dan budaya integritas yang kuat di kalangan masyarakat.
Dalam hal penerapan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, ada pengaturan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang meliputi perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pembbanti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (untuk pelaku korporasi), dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.
Efektifitas pembayaran uang pengganti dalam praktiknya masih menjadi tantangan. Banyak terpidana korupsi yang lebih memilih menjalani pidana penjara tambahan subsider daripada membayar uang pengganti, sehingga kerugian negara tidak terpulihkan secara optimal. Data menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti masih rendah dibandingkan dengan total kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di Indonesia.
Sementara itu, Singapura menerapkan sanksi pidana yang tegas untuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 dan 6 PCA, seseorang yang terbukti bersalah melakukan korupsi dapat dijatuhi hingga S$100.000,00 (seratus dolar Singapura) atau pidana penjara hingga 5 (lima) tahun, atau keduanya, untuk setiap dakwaan korupsi. Untuk korupsi yang terkait dengan kontrak atau proposal kontrak dengan pemerintah atau lembaga publik, sanksinya diperberat menjadi denda hingga S$100.000,00 atau pidana penjara hingga 7 (tujuh) tahun, atau keduanya.
Pasal 13 PCA juga mengatur penalty order yang mewajibkan terpidana membayar denda sebesar nilai suap yang diterima. Penalty order ini bersifat kumulatif dengan pidana penjara atau pidana denda, dan jika tidak dibayar dapat mengakibatkan pidana penjara pengganti (subsider) hingga 30 (tiga puluh) tahun untuk setiap penalty order. Mekanisme ini memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat mempertahankan keuntungan ilegal yang diperolehnya dari hasil korupsi tersebut, sekaligus memberikan efek jera yang kuat kepada pelakunya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya.
Court of Appeal Singapura melalui kasus Clarence Chang Peng Hong pada Desember 2024 memutuskan bahwa penalty order harus dikenakan secara terpisah untuk setiap dakwaan korupsi, bukan satu penalty order untuk keseluruhan dakwaan korupsi. Keputusan ini meningkatkan beban finansial dan pidana penjara subsider bagi pelaku korupsi.
Selain sanksi pidana, pegawai pemerintah di Singapura yang terlibat korupsi juga dapat dikenai sanksi administratif dan disipliner, termasuk pemecatan dari jabatan, pemnurunan pangkat, penghentian atau penundaan kenaikan gaji, denda, atau teguran. Instruction Manual yang dikeluarkan pemerintah juga melarang perusahaan yang terbukti terlibat korupsi dengan pejabat publik untuk mengikuti tender kontrak pemerintah, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak yang telah diberikan dan penuntutan ganti kerugian,
Mekanisme perampasan aset di Singapura diatur dalam Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA), yang memberikan kepada Pengadilan untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk aset yang telah dipindahkan atau disembunyikan. CDSA juga memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dalam kasus tertentu, namun mekanisme ini jarang diterapkan, mengingat tingkat penuntutan yang sangat tinggi di Singapura.
Indonesia sendiri sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme NCB ini lebih efektif dan efisien dalam pengembalian aset karena tidak lagi fokus mengejar pelaku, tetapi mengikuti aliran uang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengembalian kerugian negara. Namun, RUU Perampasan Aset ini masih menuai perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia dan prinsip praduga tidak bersalah.
Pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi di Singapura dilakukan melalui mekanisme penalty order dan perampasan aset berdasarkan CDSA. Singapura juga aktif dalam kerjasama internasional untuk pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri.
Indonesia membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal (predicate crime) nya adalah korupsi, dan/atau tindak pidana yang dalam peraturan perundang-undangan lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali beroperasi pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khusus menangani perkara yang diajukan oleh KPK. Komposisi majelis hakimnya terdiri dari 5 (lima) hakim: 2 (dua) hakim karir dan 3 (tiga) hakim ad hoc. Komposisi ini dirancang untuk mengatasi persoalan dalam tubuh peradilan yang dianggap cenderung korup, dengan hakim ad hoc yang berasal dari luar korps peradilan yang diharapkan dapat meningkatkan objektifitas putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memperluas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, sehingga tidak lagi hanya terpusat di Jakarta. Selain perkara-perkara yang diajukan oleh KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah juga menangani perkara yang diajukan oleh Kejaksaan. Perluasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses keadilan dan percepatan penanganan kasus korupsi di daerah.
Namun, perluasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengalami kendala sumber daya manusia, sehingga Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tidak lagi mewajibkan komposisi majelis hakim yang mayoritasnya hakim ad hoc, melainkan memberi diskresi kepada ketua pengadilan tingkat pertama untuk menentukan komposisi majelis hakim secara kasus per kasus.
Singapura tidak memiliki pengadilan khusus untuk menangani kasus korupsi. Semua kasus korupsi diadili melalui sistem peradilan pidana umum yang masuk ke District Court atau High Court, tergantung pada beratnya bobot kasus. Meskipun tidak memiliki pengadilan khusus, sistem peradilan Singapura dikenal sangat efisien dan efektif dalam menangani kasus korupsi.
Proses peradilan di Singapura berlangsung cepat dan efisien. Meskipun tidak ada tenggat waktu khusus yang ditetapkan dalam PCA, sistem peradilan yang terorganisir dengan baik, sumber daya yang memadai, dan profesionalisme tinggi dari hakim dan jaksa memastikan bahwa kasus korupsi diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Sistem peradilan Singapura juga dikenal independen dan bebas dari intervensi publik. Chief Justice (setara Ketua Mahkamah Agung di Indonesia) diangkat oleh Presiden atas saran Perdana Menteri dan Council of Presidential Advisers, sementara hakim distrik dan magistrat diangkat oleh Presiden atas saran Chief Justice. Berbagai ketentuan dalam Konstitusi Singapura menjamin independensi peradilan, dan dalam praktiknya tidak ada intervensi politik terhadap putusan pengadilan dalam kasus korupsi.
Hakim di Singapura dalam menjatuhkan putusan menerapkan prinsip deterensi, dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada terpidana untuk memerikan efek jera. Singapore High Court (setara Mahkamah Agung di Indonesia) juga secara berkala mengeluarkan kerangka kerja pemidanaan (sentencing framework) untuk memastikan konsistensi putusan.
Berdasarkan uraian di atas, ndonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektifitas pemberantasan korupsi, diantaranya:
- Kehendak politik (political will) yang tidak konsisten dan sering berubah, tergantung kepada kepemimpinan politik. Meskipun KPK dibentuk dengan tujuan mulia untuk memberantas korupsi, berbagai upaya pelemahan melalui revisi undang-undang dan intervensi politik menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi masih belum stabil;
- Budaya korupsi yang masih mengakar dalam birokrasi dan kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjadi sistemik dan endemik, denga akar historis yang panjang sejak era kolonial hingga sekarang. Mengubah budaya yang telah mengakar memerlukan waktu yang panjang dan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- Sistem remunerasi pegawai pemerintah dan pejabat negara yang masih rendah dibandingkan sektor swasta, sehingga menciptakan insentif untuk melakukan korupsi guna memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun telah ada reformasi birokrasi dan penyesuaian gaji, tingkat remunerasi pegawai pemerintah dan pejjabat negara Indonesia masih jauh di bawah standar yang dapat mencegah korupsi secara efektif.
Oleh karena itu, sebagai rekomendasi, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik (best practices) dari Singapura dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi, yakni dencan cara:
- Konsolidasi kelembagaan dengan menyederhanakan struktur lembaga antikorupsi menjadi satu lembaga tunggal yang memiliki kewenangan penuh, independent dan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Model CPIB yang beroperasi sebagai satu-satunya lembaga antikorupsi di Singapura terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan model multi-institusi Indonesia.
- Penguatan independensi lembaga antikorupsi melalui jaminan konstitusional yang kuat dan mekanisme pengawasan yang transparan namun tidak menghambat kinerja lembaga antikorupsi itu sendiri. Indonesia perlu mengamandemen ketentuan mengenai KPK untuk memastikan independensi penuh dan menghilangkan potensi intervdnsi politik, sebagaimana CPIB dijamin independensinya oleh Pasal 22G Konstitusi Singapura.
- Penyederhanaan konsep kerugian negara, dengan tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur wajib dalam semua jenis tindak pidana korupsi. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Singapura yang lebih fokus pada tindakan pemberian atau penerimaan gratifikasi yang bersifat korup, menyederhanakan proses pembuktian dan menghindari perdebatan teknis mengenai perhitungan kerugian negara.
- Peningkatan remunerasi pegawai pemerintah, pejabat negara dan penegak hukum ke tingkat yang kompetitif dengan sektor swasta, untuk mengurangi insentif melakukan korupsi. Sistem remunerasi yang baik merupakan salah satu pondasi penting dalam pencegahan korupsi, sebagaimana diterapkan di Singapura.
- Penguatan edukasi antikorupsi sejak dini melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan dan kampanye kesadaran publik secara luas dan berkelanjutan. Perubahan budaya memerlukan waktu yang panjang dan harus dimulai dari pembentukan karakter anak sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun informal.
- Percepatan pengesahan dan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset yang mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) untuk meningkatkan efektifitas pengembalian aset hasil korupsi. Mekanisme NCB telah terbukti efektif di berbagai negara, termasuk Singapura melalui CDSA, dalam mempercepat pengembalian aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Referensi
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Artikel
Aji Rahmadi, dkk., “The Concept of State Economic Loss in Corruption Crime”, Atlantis Press, 2024, hal. 361-368, Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 24 Desember 2024.
Aksi Sinurat, “The Existence of Criminal Fine and Payment of Replacement Money in Enforcing Corruption Criminal Laws in the Corruption Court in Kupang, Indonesia”, Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 12, No. 1, 2024.
Alfaizah Sabani Hasanah Suardi, dkk., “Legal Analysis of Reverse Burden of Proof in Corruption Criminal Acts in the Jeneponto District Prosecutor’s Office”, Legal Dialogica, Vol. 1, Issue 1, 2025.
Anwar Sadat, “The Application of the State Financial Losses’ Assessment in Corruption Crime After the Verdict of the Constitutional Court No. 31/PUU-X/2012”, Indonesian Journal of Sustainability, Vol. 1, No. 1, 2022.
Genoveva Puspitasari Larasati, “Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Ciminal Acts of Corruption”, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 25, Issue 2.
Mahardika Hariadi dan Luqman Wicaksono, “Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura”, Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 3, 2013.
SitusInternet
Centre for Public Impact, “Indonesia’s Anti-Corruption Commission: The KPK”, 29 Juli 2025,, https://centerforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/indonesia-anti-corruption-commission-the-kpk/.
Constitution of the Republic of Singapore, Article 22G; Channel News Asia, “Inside the CPIB: Meet the Officers Tackling Corruption in Singapore”, 13 Agustus 2024, https://www.channelnewasia.com/singapore/cpib-inside-look-investigation-officers-corruption-5290531.
CPIB, “About CPIB”, https://www.cpib.gov.sg.
CPIB, “Corruption Situation in Singapore Firmly Under Control”, Press Release, tanggal 4 Mei 2022, https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/050522-corruption/.
CPIB, “Firm Enforcement, Strong Parnerships Key to Securing a Corruption-Free Singapore”, 27 Mei 2025, https://www.cpib.gov.sg/firm-enforcement-strong-partnership-key-to-securing-a-corruption-free-singapore/.
CPIB, “Management of Corruption Complaints”, https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-education/management-of-corruption-complaints/.
CPIB, “Prevention of Corruption Act”, https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/prevention-of-corruption-act/.
CPIB, “Singapore’s Corruption Control Framework”, https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/.
David Sun, “Businessman, former BP manager get 4½ years jail eacht for graft”, https://www.cpib.gov.sg/files/news/20210512_st_business_former%20bp%20manager%20get%204%20and%20a%20half%20years%20jail%20each%20for%20graft.pdf.
KPK, “KPK: Kerugian Negara Meingkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 16 Juli 2025, http://www.mkri.id/berita/kpk-kerugian-negara-meningkat-signifkan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497,
KPK. “Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun”, 29 September 2025, https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun.
Norton Rose Fullbright, “Getting the Deal Through – Anti-Corruption Regulation in Singapore 2016”, Mei 2016, https://www.nortonrosefullbright.com/en-us/knowledge/publications/74306523/getting-the-deal-through—anti-corruption-regulation-in-singapore-2016.
Transparency International, “Corruption Perception Index 2024”, transparency.org/en/cpi/2024.
Yi Lin Seng dan Andrew Martin, “Anti-Corruption in Singapore”, Baker McKenzie Singapore, Global Compliance News, 13 Mei 2017, https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-singapore/.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI