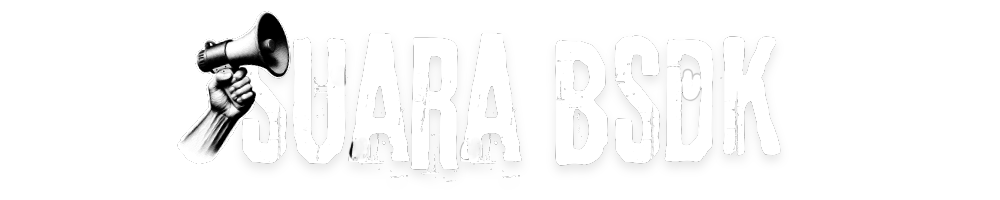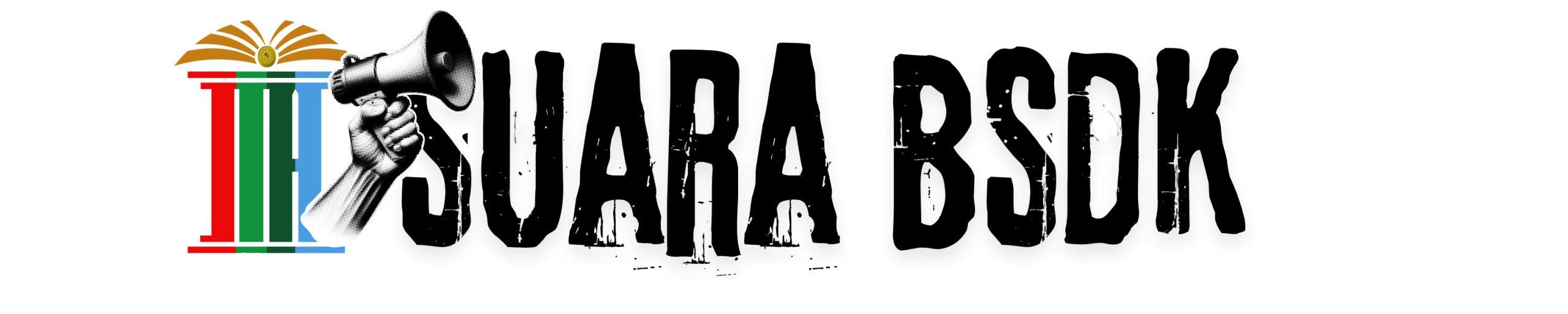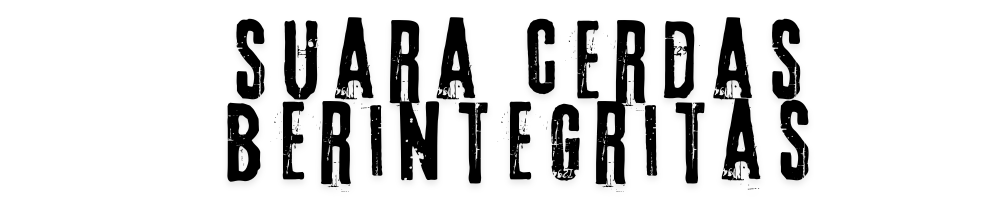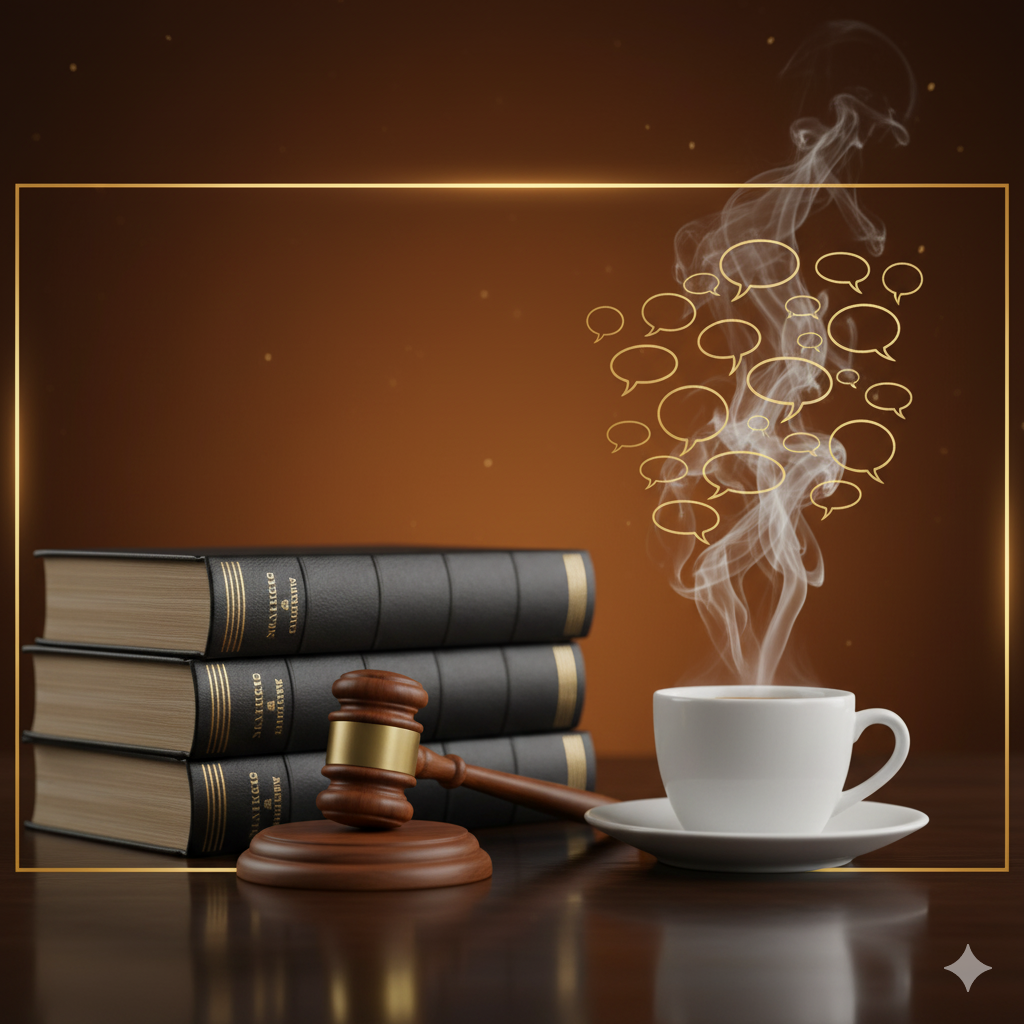(Alunan suara gemericik hujan) menikmati rintikan hujan di café kekinian yang terletak ditepian terasering di daerah Ubud, Bali dengan secangkir kopi, sungguh momen yang tidak dapat digantikan oleh apapun, seperti jentikan jari pada gitar dari seorang Piyu Padi, seperti suara camar di pagi hari dan nikmatnya senja di pantai Sanur. Sungguh momen ilahi yang menggugah romantisme ragawi hingga berujung rasa syukur atas nikmat dunia fana.
Dalam sudut pandang filosofi, “Kopi adalah refleksi nilai kehidupan”, itulah setitik makna dari Buku Filosofi Kopi yang populer dan ditulis oleh Dee Lestari. Sebagai refleksi nilai kehidupan, maka kopi memiliki makna dan simbol dari kehidupan itu sendiri, seperti:
- Rasa pahit tidaklah selalu buruk (pahitnya hidup adalah pembelajaran menuju kebaikan);
- Proses akan menentukan rasa (menikmati hidup sama dengan menikmati proses hukum dengan kesabaran dan bukan keputusan yang tergesa-gesa);
- Sederhana yang mendalam (mengajarkan kontemplasi dalam hal yang tampak biasa).
Kopi, sebagai tumbuhan yang berasal dari negara Ethiopia sekira abad ke-IX Masehi yang secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang anak penggembala kambing bernama Kaldi, dimana kambing-kambing yang digembalanya lebih bersemangat setelah memakan buah berwarna merah dari sebatang pohon (yang saat ini dikenal dengan kopi). Kopi pada tahun 1696 akhirnya masuk dan dikenal luas di Nusantara setelah dibawa oleh bangsa Belanda, dengan kata lain buah kopi yang saat ini hampir setiap hari dinikmati oleh para pecinta kopi yang berasal dari bermacam-macam usia baik yang lawas (Gen opa oma) maupun yang muda (Gen Z) bukanlah tanaman asli yang berasal dari Nusantara seperti halnya Amicus Curiae.
Amicus Curiae berasal dari bahasa latin yang secara harfiah memiliki arti “sahabat pengadilan” atau friend of court atau Amicus brief adalahpihak ketiga yang bukan termasuk pihak berperkara, yang memberikan legal opinion, informasi tambahan maupun pendapat ahli dari berbagai macam disiplin ilmu yang ditujukan kepada pengadilan dengan maksud membantu hakim menganalisis isu hukum yang kompleks dari perspektif lain. Sebagai “bestienya” pengadilan ternyata cikal bakal pemahaman mengenai Amicus Curiae hadir di negara-negara yang termasuk dalam tradisi hukum Common Law (seperti Inggris dan Amerika Serikat), namun dalam perkembangan dan praktek baiknya saat ini eksistensi pemahaman mengenai Amicus Curiae mulai hadir dalam beberapa perkara yang disidangkan di Mahkamah Agung, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer serta Mahkamah Konstitusi.
Pada dasarnya regulasi yang mengatur Amicus Curiae di Indonesia tidak secara langsung ada dalam hukum acara pidana (peradilan umum maupun peradilan militer), namun demikian dalam prakteknya telah diakui semangat dari Amicus Curiae yang terdapat di beberapa aturan hukum, diantaranya:
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, frasa “wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan” adalah landasan bagi hakim untuk membuka persepsi lain dalam menilai rasa keadilan dan nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yaitu pada Pasal 8 ayat (2) “Dalam pemeriksaan permohonan, hakim dapat meminta keterangan atau pertimbangan dari lembaga terkait atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya”, frasa “pihak lain” dalam pasal tersebut menjadi dasar hukum adanya pengakuan peran Amicus Curiae dalam hukum acara pidana di Indonesia.
Dalam kajian filosofi, Amicus Curiae adalah voice of morality dari keadilan yang substantif dan kesadaran yang mendalam seperti filosofi kopi yang mengandung makna dan nilai kehidupan:
“Hukum tanpa rasa adalah kopi tanpa aroma = Sah secara prosedural, namun hampa secara moral”.
Dalam menerima Amicus Curiae apakah hakim secara moral wajib untuk mempertimbangkannya dalam putusan? Apakah ini akan menjadi liar, sehingga menjadi kutu yang merongrong kemandirian hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara?
Dalam kajian norma hukum, Amicus Curiae bukanlah alat bukti melainkan perspektif lain (tergantung relevansi dan nilai argumentatifnya) yang dapat dipakai oleh hakim untuk memberikan keadilan yang substantif karena hukum tidak boleh berhenti pada teks semata, namun harus menyentuh rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka sudah sewajarnya hakim secara moral memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang dapat diperoleh dari perspektif pihak lain yang netral, tanpa khawatir akan menggerus kemandirian dirinya dalam mengadili suatu perkara. Dengan adanya norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, maka secara moral hakim selaku pengadil berkewajiban mempertimbangkan substansi Amicus Curiae sebagai refleksi pencarian kebenaran yang utuh. Sintetisnya, hukum seharusnya tidak hanya tepat secara prosedural, namun juga tepat rasa, hukum yang menyentuh nurani dan keadilan masyarakat, sehingga adil tidak hanya di atas kertas ataupun omon-omon belaka seperti kisah pujangga yang fiksi, tetapi juga hidup dan berkembang dalam kehidupan yang nyata. Untuk itulah hakikat dari Amicus Curiae seperti filosofi kopi yang dalam pandangan hukum yaitu kedua-duanya merupakan jalan untuk mencari kebenaran substantif yang menuntun pada nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, gabungan akal dan rasa, yang tidak memihak serta semata-mata hanya untuk memastikan rasa keadilan yang sejati itu dapat disajikan.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI