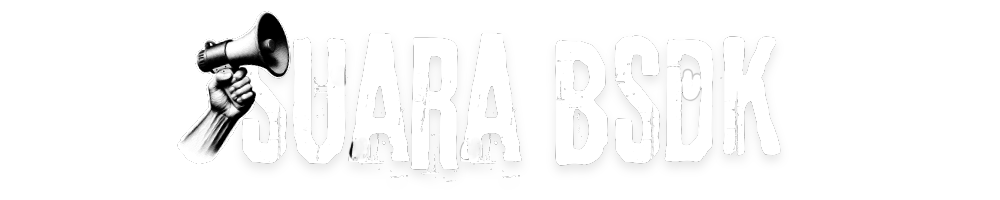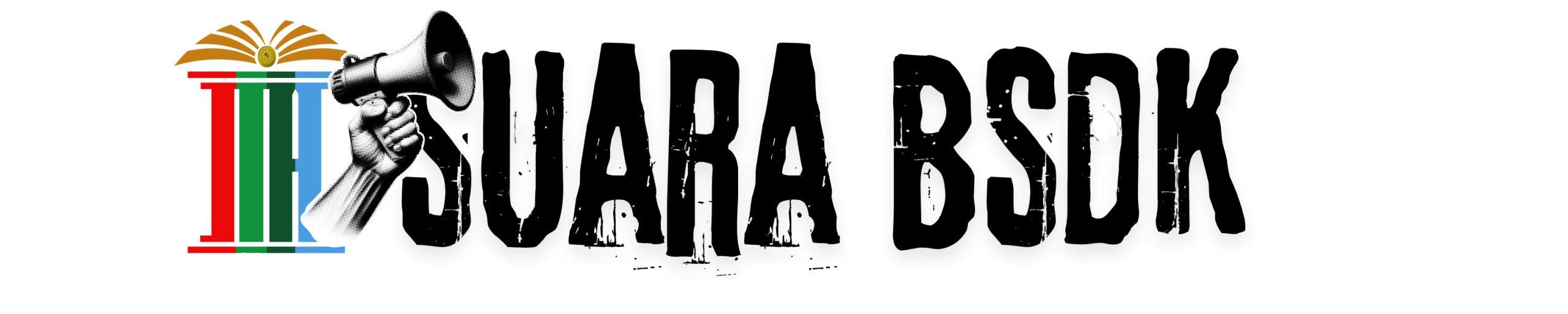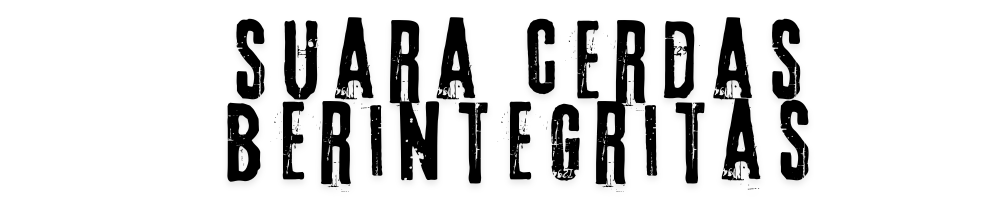Saat ini Hak Azasi Manusia (HAM) telah menjadi bahasa sehari-hari, baik di kalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. Ia bukan lagi milik ekslusif kaum aktivis HAM maupun kalangan hukum. Juga bukan lagi semacam “kata kotor” dalam leksikon politik Indonesia. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan diharapkan memberi peluang dan mengkristalkan ke arah suatu pembentukan human rights culture dalam masyarakat Indonesia di masa depan.
Dari berbagai tulisan menunjukkan bahwa, persoalan HAM sudah diperbincangkan orang sejak ratusan tahun silam diberbagai penjuru dunia, baik oleh bangsa barat maupun bangsa timur. Ini berarti, bahwa sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual, HAM tidak lahir dengan ditandatanganinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Sebab, HAM merupakan hak dasar yang sudah dimiliki oleh setiap manusia semenjak ia lahir di dunia. Dapat dikatakan bahwa, UDHR merupakan pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk selalu mengingat, menyadari, dan menghormati, serta sekaligus menegakkan HAM demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia.
Sebagai asal-usul konsep HAM dan perlindungan HAM yang modern, berlakunya teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati (hukum alam) dari John Locke dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika dan Perancis pada abad ke-17 dan abad ke-18. Ada tiga hal penting diantara sejumlah tema dan konsep yang muncul dalam Undang-Undang HAM yang berasal dari Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Pertama, bahwa hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka manusia dan bukan karena sebagai subyek hukum suatu negara. Kedua, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri yang bersifat politis yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Perancis menegaskan bahwasanya perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai dalam batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, bahwa batas-batas pelaksanaan hak dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari konsep Rule of Law yang mensyaratkan bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah harus mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak boleh bersifat menindas, sewenang-wenang atau diskriminatif.
Dalam perkembangan faham HAM, menurut Franz Magnis Suseno ada tiga unsur yang mencolok. Pertama, bahwa faham itu sendiri terbentuk dalam situasi sosial tertentu. Kedua, bahwa saat itu adalah permulaan revolusi kebudayaan terbesar dan paling radikal dalam sejarah manusia yang kita ketahui, yakni terwujudnya masyarakat modern. Ketiga, bahwa HAM demi HAM dan juga perspektif pemahaman hakikat HAM itu sendiri merupakan hasil perjuangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perkembangan kesadaran terhadap HAM mengikuti gelombang terobosan-terobosan cara berpikir manusia modern.
Kesadaran akan HAM merupakan reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi kemanusiaan yang hakiki. Melalui faham HAM, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam hukum dan politik. Tidak dapat dibantah, bahwa seperti semua tradisi normatif, maka tradisi HAM merupakan produk zamannya. Sesuai dengan kontekstualitasnya, HAM dipahami dan dirumuskan bergantung pada tantangan, ancaman dan rangsangan sosial zamannya.
Untuk memahami dengan benar perdebatan mengenai isi dan ruang lingkup yang sah dari HAM, serta prioritas-prioritas yang dituntut, maka dapat mengacu pada gagasan mengenai “tiga generasi HAM” yang diajukan oleh Karel Vasak, ahli hukum Perancis. Diilhami oleh tiga tema normatif Revolusi Perancis, Vasak membagi perkembangan HAM dalam tiga generasi. Pertama, kebebasan (liberte) merupakan generasi pertama HAM, yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik. Kedua, persamaan (egalite) adalah HAM generasi kedua, yang terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, solidaritas (fraternite) sebagai HAM generasi ketiga, yang terdiri dari hak atas pembangunan, hak atas identitas kultural, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas partisipasi pada warisan bersama umat manusia dan hak generasi mendatang atas keselamatan lingkungan hidup.
Generasi pertama muncul pada abad ke-17 dan abad ke-18 berkaitan dengan Revolusi Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis sebagai penolakan terhadap absolutisme raja-raja pada masa itu. Ketiga revolusi ini melahirkan konsep demokrasi dan negara hukum, yang intinya adalah kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Generasi pertama HAM lebih menitikberatkan pada hak-hak manusia sebagai individu, sesuai dengan dasarnya, yaitu individualisme dan liberalisme. Generasi kedua muncul pada abad ke-18 sebagai tanggapan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang mendasarinya, yang pada pokoknya mentolerir bahkan mengesahkan eksploitasi kelas pekerja dan rakyat daerah jajahan. Dengan kata lain, ide kebebasan dan individualisme telah merasionalisasikan kekejaman kapitalisme. Menurut sejarah, generasi kedua merupakan titik balik terhadap generasi pertama, yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik, dengan HAM dipahami lebih dalam istilah-istilah yang positif (hak atas) daripada negatif (bebas dari) yang mensyaratkan intervensi, bukan abstensi negara, dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dikandungnya. Dalam kaitannya dengan demokrasi dan negara hukum, tuntutan generasi kedua HAM menghasilkan apa yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan negara hukum yang dinamis. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya rakyat, konsep negara kesejahteraan dan negara hukum yang dinamis memberi peran aktif kepada negara untuk mengatur dan intervensionis melalui prinsip freies ermessen, sehingga menampilkan diri sebagai negara kuat. Akibat negatifnya, kebebasan individu yang menjadi dasar hak-hak sipil dan politik ditekan oleh negara. Generasi ketiga HAM muncul abad ke-20 yang menghubungkan dan mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi HAM terdahulu. Munculnya HAM generasi ketiga ini dilatarbelakangi oleh chauvanisme, primordialisme, totalitarianisme, dan penindasan kelompok minoritas sebagai akibat dari pertumbuhan dunia ketiga yang cenderung berat ke ekonomi dan mengabaikan faktor non-ekonomi.
Hak-hak asasi yang umumnya dipahami menurut pengertian-pengertian sosial, ekonomi, maupun politik, sekaligus merupakan sebuah tujuan yang lebih serius dan kurang bisa dimengerti ketimbang konstitusionalisme, meskipun keseluruhannya bisa memberikan keseimbangan yang lebih baik dan standar yang lebih tepat. Tidak ada konstitusi yang dengan sendirinya bisa menjamin hak-hak politik, tanpa mengabaikan keadilan sosial dan ekonomi.
Dengan lahirnya HAM generasi ketiga semua hak yang terdapat dalam HAM generasi pertama (hak-hak sipil dan politik) dan hak dalam HAM generasi kedua (hak-hak ekonomi, sosial dan budaya), disatukan dan mempunyai kedudukan yang sama. Todung Mulya Lubis dalam bukunya yang berjudul “Hak Asasi Manusia dan Pembangunan” berpendapat bahwa hak yang demikian dapat disebut sebagai hak akan pembangunan (the right to development).
Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional di satu sisi dan dalam rangka menanggulangi permasalahan bangsa yang ditimbulkan oleh paradoksalitas nilai global dengan nilai nasional yang berlaku selama ini di sisi lain, tidak ada hal penting untuk dilakukan oleh bangsa Indonesia kecuali mempelajari dan memahami dengan benar nilai-nilai global (universal) dan nilai-nilai nasional yang berlaku selama ini, kemudian menerima kebenaran itu dan melaksanakannya dalam kehidupan nyata berdasarkan semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Demokrasi dan HAM merupakan konsep universal mengenai kewajiban untuk menghormati, menghargai dan melindungi individu manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khusus dalam kehidupan bernegara, substansi demokrasi dan HAM teraktualisasi dalam hubungan warga negara dengan negara yang berwujud partisipasi warga negara dan perlindungan terhadap HAM warga negara oleh negara.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI