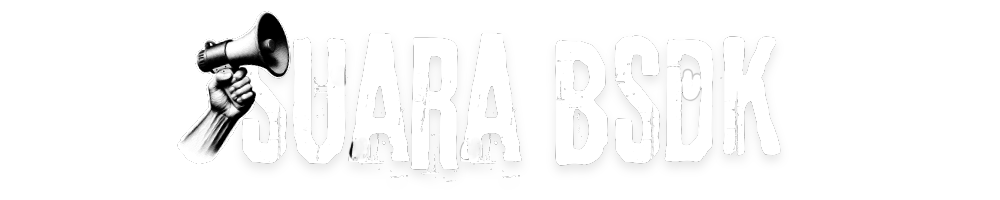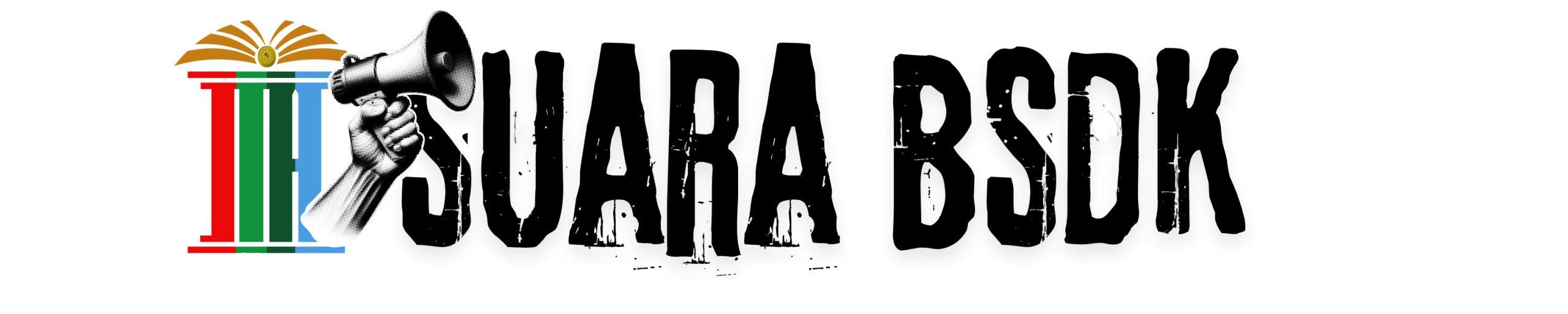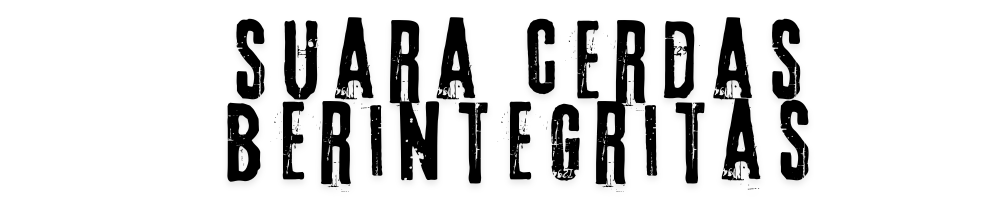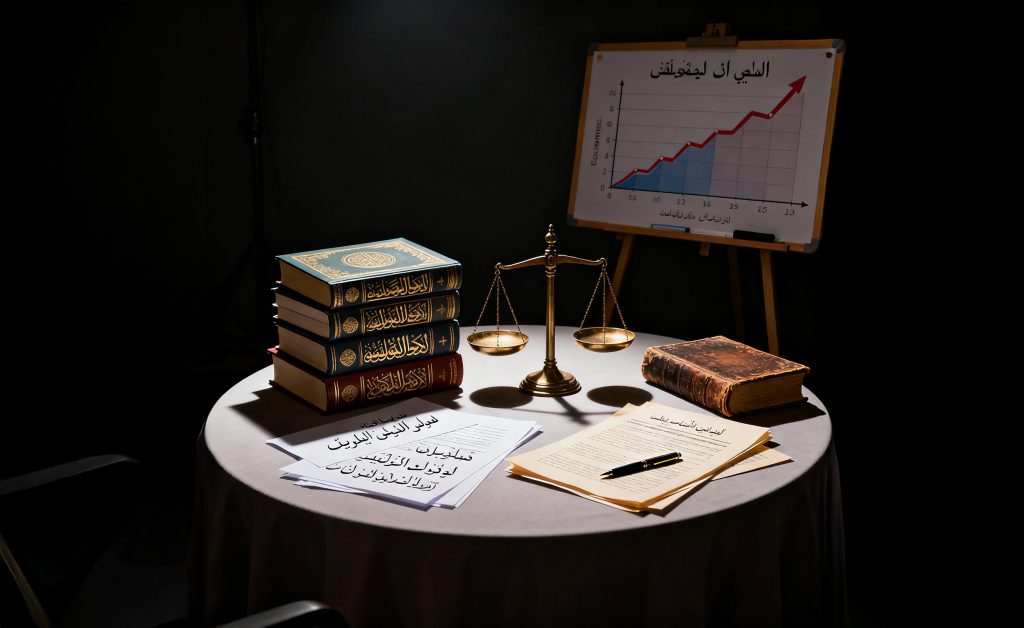Pendahuluan
Setiap orang memiliki hak asasi yang diakui secara universal, termasuk di dalamnya adalah hak untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kesejahteraan hidupnya. Menurut John Locke,[1] seorang tokoh hak asasi manusia, meskipun negara memiliki “kekuasaan” yang lahir dengan didasari teori kontrak sosial, akan tetapi kekuasaan negara adalah terbatas. Artinya, negara tidak boleh mengganggu bahkan negara harus melindungi hak asasi manusia yang secara individu memiliki hak alamiah (natural right), yaitu hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan kekayaan (property).
Hak asasi manusia (HAM) pertama yang populer adalah hak individu dan politik (individual and political right). Oleh karenanya, dikenal dengan hak asasi generasi pertama. Kemudian dalam dinamika perkembangan HAM, dikenal hak asasi generasi kedua, yaitu hak sosial dan ekonomi (social and economy right).[2] Dengan demikian, hak ekonomi dan sosial juga termasuk HAM.
Hak asasi mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka negara menjamin hak asasi ekonomi setiap warga negaranya dengan melindungi dan memberi kebebasan warga negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, tidak saja dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada sistem ekonomi konvensional, tetapi juga kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam (ekonomi syariah).[3]
Masyarakat mulai tertarik dengan sistem ekonomi syariah karena menawarkan konsep adil (fair) yang saling menguntungkan dengan menghindari sistem ketidakpastian (gharar), unsur perjudian (maisir), dan bunga. Masyarakat juga mulai tertarik kepada lembaga keuangan syariah (LKS), terutama bank syariah karena prospek dan ketangguhan LKS teruji ketika melewati era krisis ekonomi. Sebagaimana diketahui, ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi pun meninggi sehingga bunga perbankan mengalami kenaikan yang berlipat, tidak sesuai dengan prediksi dalam keadaan normal (tidak terjadi krisis ekonomi). Namun, lembaga keuangan dengan berbasis syariah tetap bertahan dengan baik ketika terjadi krisis ekonomi karena sistem syariah tidak mengenal adanya bunga.
Sedangkan lembaga keuangan (LK) lain yang non-syariah, banyak yang tidak tahan terhadap gempuran krisis ekonomi yang disebabkan memakai sistem bunga yang tidak tahan menghadapi inflasi yang sangat drastis dan suku bunga yang tinggi ketika terjadi krisis ekonomi.[4] Ketangguhan LKS juga teruji ketika melewati masa pandemi, yaitu perbankan syariah di Indonesia tangguh dalam menghadapi krisis Covid-19.[5] Fenomena ini menjadikan perkembangan LKS semakin pesat yang menggambarkan banyaknya praktik hukum muamalah di kalangan umat Islam. Banyaknya praktik hukum muamalah tersebut adalah suatu hal yang positif dalam hal perkembangan ekonomi Indonesia.
Dengan perkembangan yang demikian pesat tersebut, hukum hadir, salah satunya dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan dengan maksud dapat mengatur kegiatan ekonomi tidak saja sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang lain mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip syariah.[6] Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, lahir pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan bentuk respons positif Mahkamah Agung atas perkembangan positif kegiatan ekonomi syariah. Respons tersebut dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Mahkamah Agung, yakni mengatur, di samping fungsi yang lain, yaitu fungsi peradilan dan pengawasan.
Berdasarkan fungsinya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 guna memperlancar jalannya proses peradilan. Dengan demikian, berarti fungsi mengatur yang ada pada Mahkamah Agung juga dijalankan untuk mendukung fungsi yang lain, yaitu fungsi peradilan.
Meskipun masih berpayung hukum peraturan Mahkamah Agung (Perma), eksistensi KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di peradilan agama karena saat lahir KHES belum ada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang yang memuat substansi hukum seperti dalam KHES. Dari sisi substansi, KHES terdiri atas 3 (tiga) buku, 39 bab, dan 790 pasal yang disusun dengan merujuk dari berbagai kitab fikih, termasuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan Bank Indonesia.
Pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, dinamika kegiatan ekonomi syariah masyarakat terus berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat sehingga berdampak pula terhadap semakin tingginya penggunaan barang dan jasa yang halal. Visi Indonesia yang dicanangkan pemerintah yaitu Indonesia sebagai “Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Dunia” menunjukkan dukungan positif pemerintah terhadap ekonomi syariah dan semakin menambah pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam kenyataannya telah banyak memunculkan konsep baru dalam perumusan norma-norma akad-akad syariah yang menopang kegiatan keuangan dan bisnis syariah. Beberapa konsep baru memang telah diatur dalam KHES, tetapi banyak juga yang belum terakomodasi bahkan ditemukan juga yang bertentangan dengan norma-norma akad yang ada pada KHES.
Industri halal yang telah menjadi gaya hidup (lifestyle) masyarakat dunia merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk merespons dan menangkap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari maraknya industri halal tersebut. Namun, Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang muslim dirasa masih lambat dalam merespons dan menangkap kesempatan tersebut. Salah satu faktor yang menjadi pemicu lambatnya respons tersebut adalah kurangnya dukungan dari negara (pemerintah) dari segi regulasi yaitu belum ada standar hukum yang jelas dan masih kurang memadai.[7]
Di samping hal tersebut, beberapa fatwa dari DSN-MUI juga telah banyak dikeluarkan, tetapi secara substansi belum termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah ada.
Persoalan lain yang juga muncul adalah adanya beberapa hal yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi karena adanya dinamika perkembangan masyarakat, hal tersebut tidak lagi sejalan dengan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang keluar belakangan.
Meskipun kekurangan substansi dari KHES yang ada dapat ditutupi dengan adanya yurisprudensi,[8] akan tetapi adanya yurisprudensi muncul setelah timbulnya sebuah sengketa yang masuk ke pengadilan, sedangkan hadirnya hukum diharapkan secara dini agar dapat mengantisipasi adanya sengketa. Lagi pula, jika belum ada ketentuan yang belum dinormakan, maka masih membuka peluang adanya disparitas (perbedaan) putusan.
Upaya penyempurnaan substansi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salah satu ikhtiar dalam pembaruan hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan untuk menyikapi perkembangan masyarakat yang ada dengan mewujudkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, di samping juga membantu kelancaran dunia usaha (ease of doing business),[9] membuka peluang banyaknya investasi dan membantu dalam pembangunan ekonomi, serta pada gilirannya membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Landasan Filosofis Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki landasan filosofis yang kuat karena: pertama, sesuai cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945; kedua, pengembangan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sistem ekonomi yang melibatkan semakin banyak masyarakat yang terlibat (inklusi) yang akan memberikan dampak positif bagi upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional; dan ketiga, ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin (prinsip universalitas dan inklusivitas) dan prinsip maqashid al-syariah (prinsip maslahat dan keadilan sosial), sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui program-program kesejahteraan sosial dan kebijakan ekonomi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini, dan sejalan dengan tata kelola kesejahteraan dunia yang dituangkan dalam SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan secara eksplisit tujuan Pemerintah Republik Indonesia.[10] Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan pengembangan kegiatan ekonomi dan keuangan. Usaha ini dilakukan agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha yang demikian diperlukan sistem ekonomi yang memberikan ruang keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (inclusion) tanpa terkecuali. Pilihan perangkat ekonomi dan keuangan berbasis prinsip syariah adalah salah satu wujud dari sistem ekonomi yang menjadikan banyak masyarakat yang turut terlibat (inklusi). Hal demikian akan memberikan dampak yang positif bagi upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Negara Indonesia mengakui adanya dual economic & financial system yaitu konsep pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah disinergikan dengan ekonomi dan keuangan konvensional. Hal tersebut tidak saja sebagai penguatan visi pembangunan Indonesia, tetapi juga memberikan pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Adanya ekonomi dan keuangan syariah bukan sesuatu yang asing yang merupakan hal yang eksklusif, melainkan ia bersifat universal sesuai dengan prinsip universalitas dan inklusivitas serta prinsip maqashid al-syariah.[11]
Perangkat ekonomi dan keuangan berbasis prinsip syariah membuka ruang pilihan kepada masyarakat yang rasional. Ia memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas keseharian, terutama aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perangkat ekonomi dan keuangan berbasis prinsip syariah selaras dengan arah pembangunan nasional yang ditempuh melalui program-program kesejahteraan sosial dan kebijakan ekonomi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain hal tersebut prinsip ini juga sejalan dengan tata kelola kesejahteraan dunia yang dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)[12] yang kata kuncinya adalah menyinergikan tiga unsur penting, yaitu universal, integrasi (integration), dan tidak ada pihak yang tertinggal (no one left behind).
Landasan Sosiologis Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Landasan Sosiologis Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu: pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam; kedua, kebutuhan transaksi yang beragam dan tingginya dukungan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah; ketiga, adanya dukungan pemerintah yang kondusif melalui koordinator kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Kebutuhan transaksi yang beragam dan tingginya dukungan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terlihat dari perjalanan panjang dinamika kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah. Kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan syariah mengalami evolusi dan perkembangan. Pada tahap awal, kebutuhan atas transaksi keuangan syariah hanya terbatas pada bidang perbankan saja, tetapi sejalan dengan perkembangan, kebutuhan tersebut kemudian berlanjut meliputi transaksi keuangan yang tidak saja pada bidang perbankan, melainkan juga di bidang nonperbankan, baik di pasar modal maupun di industri keuangan nonbank (IKNB), termasuk pula institusi keuangan mikro dan koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan atas transaksi ekonomi dan bisnis lainnya juga tumbuh seperti penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), rumah sakit syariah, industri halal dan pariwisata syariah. Di samping hal tersebut, besarnya potensi dana-dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) juga dapat menjadi bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dengan adanya fakta dinamika yang demikian, maka kemudian muncul adanya kebutuhan mengolaborasikan dalam suatu ekosistem ekonomi syariah.
Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang komprehensif adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal acuan hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Hal demikian juga merupakan salah satu dari upaya mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang melibatkan berbagai aspek penting, salah satunya adalah substansi hukum dengan payung hukum berupa pengaturan yang dibentuk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Karena jika menilik ke belakang, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami evolusi. Bermula tumbuh dan berkembang yang hanya terbatas saja yaitu lembaga keuangan syariah,[13] bisnis dan ekonomi syariah,[14] dan lembaga-lembaga filantropi Islam.[15] Dengan demikian, menurut Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma’ruf Amin,[16] upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan kepada 4 (empat) hal, yaitu: 1) pengembangan dan perluasan industri produk halal, 2) pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah, 3) pengembangan dan perluasan dana sosial syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf) dan penguatan peran institusi keuangan mikro syariah; serta 4) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah melalui penumbuhan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Landasan Yuridis Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Landasan Yuridis Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencakup tiga hal, yaitu: 1) perwujudan konstitusional negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2) peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sangat beragam dan belum terakomodasi dalam KHES; dan 3) prinsip syariah berupa fatwa yang diterbitkan DSN-MUI jumlahnya sangat banyak dan belum terakomodasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Penutup
Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat urgen dilakukan karena memiliki landasan yang kuat yaitu:
- Landasan Filosofis
Pertama, sesuai cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, pengembangan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sistem ekonomi yang melibatkan semakin banyak masyarakat yang terlibat (inklusi) yang akan memberikan dampak positif bagi upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ketiga, ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin (prinsip universalitas dan inklusivitas) dan prinsip maqashid al-syariah (prinsip maslahat dan keadilan sosial), sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui program-program kesejahteraan sosial dan kebijakan ekonomi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini, dan sejalan dengan tata kelola kesejahteraan dunia yang dituangkan dalam SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
- Landasan Sosiologis
Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Kedua, kebutuhan transaksi yang beragam dan tingginya dukungan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
Ketiga, adanya dukungan pemerintah yang kondusif melalui koordinator kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Landasan Yuridis
Pertama, perwujudan konstitusional negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sangat beragam dan belum terakomodasi dalam KHES.
Ketiga, prinsip syariah berupa fatwa yang diterbitkan DSN-MUI jumlahnya sangat banyak dan belum terakomodasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Referensi
Abdul Manan. 2006. Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
———. 2016. Hukum ekonomi Syariah: Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
Atang Abd. Hakim, 2011, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan Bandung: Refika Aditama.
Glarence Morris, 1979, The Great Legal Philosophers, Philadelphia: University of Pennsylvania.
Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mardani, 2015, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
Miriam Budiardjo, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
JCT Simorangkir, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.
Khoirul Anwar, 2018, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah, Jakarta: Kencana.
Khudzaifah Dimyati, 2005, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
Chuzaimah Batubara dan Isnaini Harahap, Halal Industri Development Strategies Muslem’s Responses and Shariah Compliance in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, Volume 16, Number 01, June 2022, ISSN 1978-6301 and E-ISSN 2355-6994.
Darmawan, Tahqiq Al-Manath Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Al-Daulah, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 8, Nomor 1, April 2018.
Famirotul Lail1, Mohammad Ali Hisyam, Metode Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram Dalam Fatwa Dsn-Mui Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum), Jurnal Kaffa Vol. 1, No. 2 (Juni 2022)
Putra Halomoan, Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Labatila, Vol:1, No. 2, Juni 2018. Hlm. 117. https://ejournal.iainu-kebumen. ac.id/index.php/lab/article/ view/78.
Rustam Hanafi, Abdul Rohman, Sutapa, Islamic Bank Resilience: Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemi in Indonesia, Muqtasid: jurnal ekonomi dan perbankan syariah, p-ISSN 2087-7013, e-ISSN 2527-8304, Vol 13, Nomor 1 tahun 2022, hlm. 28.
Wicaksana Wahyu Prasetya, Perwujudan Asas Al Musawah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013.
Atmo Prawiro, Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Al-Ashriyyah. Volume 2. Nomor 1. Oktober 2016.
[1]Glarence Morris, The Great Legal Philosophers, University of Pennsylvania, Philadelphia, Tahun 1979, hlm. 152.
[2] Ibid, hlm. 1.436.
[3] Khoirul Anwar, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah, Kencana, Tahun 2018, hlm.1
[4] Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dunia yang juga merambah ke Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia terpuruk, harga berbagai aset menurun tajam, suku bunga melonjak tinggi.
[5] Rustam Hanafi, Abdul Rohman, Sutapa, Islamic Bank Resilience: Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemi in Indonesia, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, p-ISSN 2087-7013, e-ISSN 2527-8304, Vol 13, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 28.
[6] Menghindari maisir, gharar dan riba, serta hal-hal haram lainnya.
[7] Lihat: Chuzaimah Batubara dan Isnaini Harahap, Halal Industri Development Strategies Muslem’s Responses and Shariah Compliance in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, Volume 16, Number 01, June 2022, ISSN 1978-6301 and E-ISSN 2355-6994, hlm. 52.
[8] Yurisprudensi yang dimaksud yaitu putusan hakim dengan pertimbangan dan penerapan hukum dari substansi hukum yang belum termuat dalam KHES yang kemudian putusan tersebut diikuti oleh hakim-hakim berikutnya.
[9] Ease of doing business adalah isu yang penting untuk direspons. Reformasi bidang hukum diyakini mampu meningkatkan indeks ease of doing business yang merupakan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia guna mengukur peringkat kemudahan berusaha/berbisnis di berbagai negara.
[10] Dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa tugas pemerintah negara Republik Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
[11] Prinsip maslahat dan keadilan sosial, lawan dari mafsadat dan kedhaliman. Prinsip Maqashid al-Syariah, substansinya berupa mashlahat yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga, dan harta manusia, dan keadilan sosial.
[12] Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “Noone Left Behind”. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan lalu Lihat: https://sdgs.bappenas.go.id/
[13]Dalam hal ini, khususnya perbankan syariah (1992), Takaful/Perusahaan Asuransi Syariah (1994), Pasar modal Syariah – Produk Reksadana Syariah (1998), saham & sukuk korporasi (2003), Efek Beraguan Aset Syariah (EBAS) (2017), SBSN/Sukuk Negara (2008), Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah-KSPPS (2004), Baitul Maal Mattamwil-BMT (1990-an), dll.
[14] seperti PLBS/Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (2009), Rumah Sakit Syariah (2016), dan Pariwisaata Syariah (2016), serta Industri halal;
[15] Seperti zakat, infak, shadaqah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat), dan Wakaf (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
[16] Lihat Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2020—2024.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI