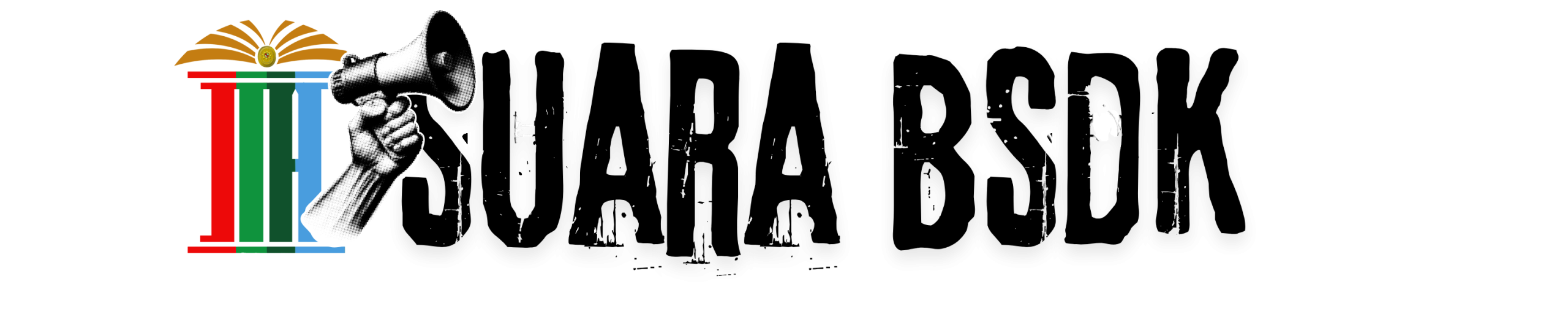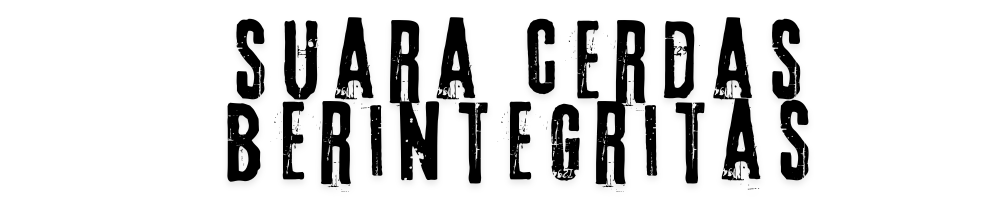Hari ini, 10 Oktober, dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day), yang telah ditetapkan oleh World Federation for Mental Health (WFMH) sejak tahun 1992. Momen ini bukan sekadar seremonial global, melainkan pengingat bahwa kesehatan mental adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang berjuang di garda depan sekaligus menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan.
Di gedung pengadilan, saat di antara toga dan palu sidang, ada manusia yang juga memikul beban berat, menanggung tekanan publik, dan berjuang menjaga kejernihan pikiran di tengah kompleksitas tugas yang tak pernah berhenti.
Hakim merupakan sumber daya utama dalam sistem peradilan. Dari integritas, intelektualitas, serta kesehatan fisik dan mentalnya lahir kualitas putusan yang menjadi harapan besar masyarakat. Namun, tekanan yang melekat pada profesi ini pun tidak kalah besar. Dalam satu hari kerja, seorang hakim dapat bergulat dengan berbagai perkara yang rumit, berdampak luas, hingga menyentuh dasar nurani. Di sisi lain, beban kerja (workload) yang tinggi, ekspektasi publik, dan sorotan media membuat ruang pribadi semakin menyempit. Tekanan semacam ini berpotensi menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai judicial burnout, yakni kelelahan emosional dan psikologis akibat akumulasi tanggung jawab yang berat dan berkelanjutan.
Budaya diam masih mengakar kuat di dunia peradilan. Membicarakan kelelahan mental sering dianggap tabu dan menimbulkan rasa malu. Seolah seorang hakim harus selalu kuat, tidak boleh lelah, apalagi goyah. Padahal, di balik sibuk dan riuh ruang sidang, banyak yang diam-diam berjuang menata batin agar tetap tenang dan seimbang. Tekanan yang tidak tersalurkan dapat berakibat pada penurunan konsentrasi, gangguan tidur, bahkan menurunnya kualitas pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kinerja yudisial (performance of judicial function), termasuk aspek penting seperti konsistensi putusan dan transparansi dalam pengambilan keputusan (lack of transparency in judicial decision). Akibatnya, tak jarang seorang hakim seringkali memutus perkara orang lain, namun lupa memulihkan diri sendiri.
Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental mulai tumbuh di berbagai lembaga peradilan dunia. Beberapa negara telah meluncurkan program judicial wellness, menyediakan layanan konseling profesional, dan menciptakan ruang aman bagi aparat peradilan untuk berbagi tanpa stigma. Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat meskipun masih pada tahap awal. Lokakarya bertemakan kecerdasan emosional, sesi manajemen stres, serta pembentukan kelompok peer support perlahan menjadi bagian dari agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia peradilan. Inisiatif seperti peer network dan mentoring program juga dapat menjadi wadah dialog terbuka (open dialogue) untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan antarsesama hakim, terutama bagi mereka yang baru diangkat atau bertugas di daerah dengan beban perkara tinggi. Melalui jejaring seperti ini, tumbuh solidaritas (creating solidarity) dan rasa kebersamaan bahwa setiap orang pernah mengalami tekanan dan layak mendapatkan ruang untuk pulih. Namun, berbagai inisiatif ini masih memerlukan dukungan struktural agar tidak berhenti pada level diskusi dan forum temu wicara, melainkan terintegrasi dalam kebijakan kelembagaan sebagai bagian dari komitmen institusi terhadap kesejahteraan yudisial (judicial well-being).
Sementara itu, kesehatan mental bukan hanya menjadi tanggung jawab individu. Ia juga menuntut perubahan struktural (structural changes) dalam tata kelola peradilan, termasuk penataan beban kerja yang lebih proporsional, sistem dukungan karier yang adil, serta pengakuan terhadap prestasi nonmateri. Penguatan kapasitas melalui pelatihan komunikasi empatik, manajemen stres, atau pengambilan keputusan etis, merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun peradilan yang berdaya dan manusiawi.
Menjaga kesehatan mental di dunia peradilan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga bentuk pengakuan institusional terhadap kemanusiaan para pelaksana fungsi yudisial. Lembaga peradilan yang berorientasi pada keadilan sejati juga memberi ruang bagi kesejahteraan mental para aparaturnya. Sebab, keadilan bukan hanya hasil dari penalaran hukum yang tepat, melainkan juga dari hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita renungkan kembali bahwa judicial well-being adalah fondasi untuk “berkeadilan.” Hakim yang sehat jiwanya akan lebih mampu mendengarkan, memahami, dan memutus dengan nurani. Peradilan yang kuat tidak lahir dari ketangguhan tanpa batas, melainkan dari keseimbangan antara tugas profesional dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, menjaga keadilan juga berarti menjaga manusia di baliknya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI