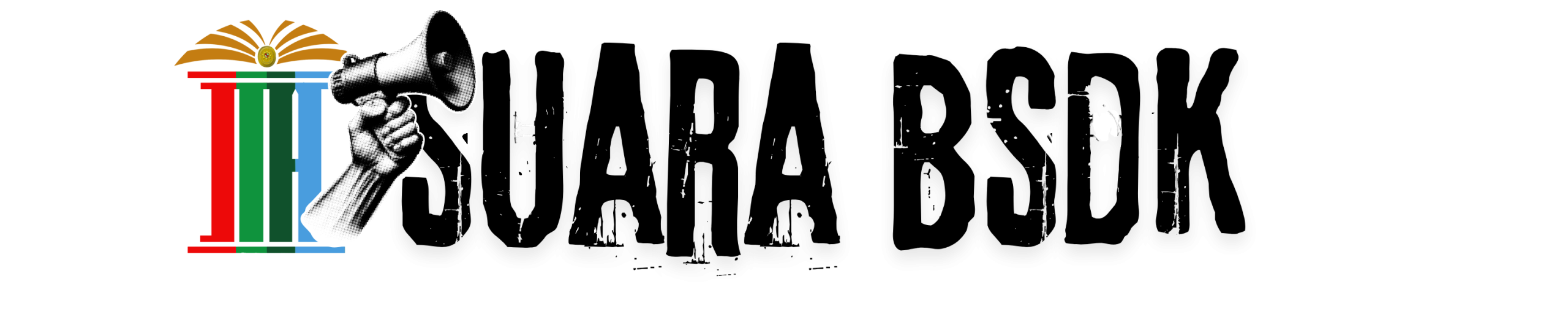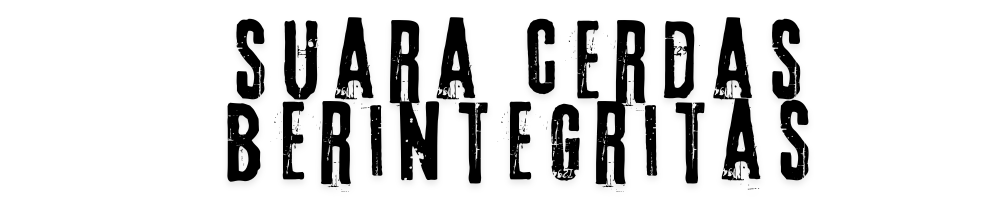Paradok Hukum Internasional
Hukum internasional dibangun dari kesadaran bahwa hubungan antar negara tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Ia lahir sebagai pagar pembatas kekuasaan, agar perbedaan kepentingan diselesaikan melalui aturan bersama, bukan melalui ancaman atau kekuatan militer. Prinsip ini menjadi fondasi tatanan dunia modern setelah pengalaman pahit dua perang dunia yang menunjukkan betapa berbahayanya politik kekuasaan tanpa hukum.
Tujuan tersebut tercermin jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan internasional harus dijaga melalui langkah-langkah kolektif. Artinya, penyelesaian konflik tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada tindakan sepihak negara, melainkan melalui mekanisme bersama yang disepakati komunitas internasional.
Namun, perkembangan global beberapa tahun terakhir memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Konflik bersenjata di Ukraina dan berbagai dugaan tindakan sepihak terhadap Venezuela menunjukkan bahwa hukum internasional kerap dipinggirkan ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara besar. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional tampak seperti cermin yang retak: masih ada, tetapi pantulannya tidak lagi utuh.
Piagam PBB secara tegas meletakkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara dalam Pasal 2 ayat (1). Tidak ada negara yang secara hukum lebih tinggi kedudukannya dibanding negara lain, terlepas dari kekuatan militer atau pengaruh politiknya. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap negara berhak atas penghormatan terhadap wilayah dan kemerdekaan politiknya.
Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang melarang ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Larangan ini merupakan norma inti hukum internasional. Perbedaan ideologi, ketidaksetujuan terhadap sistem politik, atau klaim kepentingan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikannya.
Dalam doktrin hukum internasional, pengecualian atas larangan penggunaan kekuatan hanya diberikan dalam keadaan yang sangat terbatas. Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak pembelaan diri apabila terjadi serangan bersenjata yang nyata. Namun, hak ini tidak bersifat bebas. Ia harus memenuhi syarat kebutuhan dan proporsionalitas, serta segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Pembelaan diri tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atas tindakan preventif hipotetis atau upaya perubahan rezim.
Cermin Retak Hukum Internasional
Kasus Ukraina memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dilanggar secara terang-terangan. Invasi Rusia ke wilayah Ukraina telah dinilai secara luas sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Reaksi dunia internasional berupa kecaman dan sanksi menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kesepakatan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB. Namun, konflik yang terus berlangsung juga memperlihatkan keterbatasan hukum internasional dalam menghadapi negara dengan kekuatan politik dan militer besar.
Keterbatasan ini menjadi semakin problematis ketika penerapan hukum internasional tidak konsisten. Dugaan serangan sepihak dan penahanan paksa terhadap Presiden Venezuela, apabila benar terjadi, menimbulkan persoalan hukum yang tidak kalah serius. Tindakan semacam itu berpotensi melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, sekaligus mencederai prinsip kesetaraan kedaulatan negara.
Lebih jauh, Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi, yakni larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Penentuan kepemimpinan politik dan sistem pemerintahan suatu negara merupakan bagian dari yurisdiksi domestik yang harus dihormati. Upaya menekan, mengganti, atau menahan pemimpin negara lain dengan alasan politik bertentangan dengan prinsip dasar ini.
Persoalan yang muncul bukan semata-mata pada satu tindakan tertentu, melainkan pada pola yang mulai terbentuk. Ketika agresi terhadap Ukraina dikutuk sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara tindakan serupa terhadap Venezuela dibingkai dengan narasi pembenaran politik, maka standar hukum menjadi kabur. Dalam hukum, konsistensi adalah syarat utama legitimasi. Tanpa konsistensi, hukum kehilangan otoritas moralnya.
Piagam PBB juga telah menyediakan mekanisme yang jelas terkait penggunaan kekuatan bersenjata. Pasal 39 memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Selanjutnya, Pasal 42 mengatur bahwa penggunaan kekuatan militer hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan militer tidak dimaksudkan sebagai hak individual negara, melainkan sebagai langkah kolektif.
Dalam konteks ini, tindakan sepihak tanpa mandat Dewan Keamanan tidak hanya merusak tatanan hukum internasional, tetapi juga melemahkan sistem keamanan kolektif yang dibangun PBB. Ketika negara memilih bertindak sendiri, peran PBB tereduksi dan konflik berpotensi meluas tanpa kendali. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi antara hukum internasional dan hukum nasional negara-negara besar. Di Amerika Serikat, Konstitusi secara tegas membatasi penggunaan kekuatan militer dengan menempatkan kewenangan menyatakan perang pada Kongres. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang oleh eksekutif. Selain itu, prinsip due process of law menjadi pilar utama negara hukum, yang menuntut bahwa setiap tindakan penahanan harus didasarkan pada prosedur hukum yang sah.
Darurat Kepatuhan terhadap Hukum International
Ketika tindakan di tingkat internasional bertentangan dengan prinsip konstitusional domestik, muncul pertanyaan mengenai konsistensi nilai yang dijunjung. Hukum internasional dan hukum nasional seharusnya saling memperkuat, bukan saling meniadakan. Fenomena pengabaian hukum internasional tidak hanya terjadi di Ukraina dan Venezuela. Tindakan China terhadap Tibet dan klaimnya atas Taiwan, serta keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman, menunjukkan kecenderungan serupa. Negara menggunakan kepentingan strategis untuk membenarkan tindakan yang mengabaikan prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan. Jika pola ini terus berlanjut, norma fundamental Piagam PBB berisiko kehilangan makna praktisnya.
Bagi negara-negara berkembang, situasi ini membawa konsekuensi serius. Ketika hukum internasional tidak ditegakkan secara konsisten, perlindungan terhadap kedaulatan mereka menjadi rapuh. Dalam kondisi demikian, kepatuhan terhadap hukum internasional bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan nyata untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Hukum internasional memang tidak sempurna dan tidak memiliki aparat pemaksa seperti hukum nasional. Namun, ia tetap berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi penggunaan kekuasaan. Piagam PBB memberikan panduan yang jelas: perdamaian harus dijaga secara kolektif, penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir, dan kedaulatan negara harus dihormati.
Cermin hukum internasional yang kini tampak retak seharusnya menjadi refleksi bersama. Ketika negara-negara memilih untuk menempatkan kepentingan jangka pendek di atas aturan yang telah disepakati, yang terkikis bukan hanya hukum, tetapi juga kepercayaan terhadap tatanan global. Memulihkan komitmen terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsipnya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum internasional tetap menjadi penuntun, bukan sekadar simbol, dalam hubungan antarnegara.
Referensi:
[1] United Nations. 1945. Charter of the United Nations.
[2] Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. 2013. Pengantar hukum internasional. PT Alumni.
[2] Lestari, A. P. 2016. Hukum internasional dan tantangan penegakannya dalam konflik bersenjata. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 345–360.[3] Jambak, F., et al. 2018. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional dalam perspektif Indonesia. Jurnal Strategi dan Global Studies, 2(1), 45–60.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI