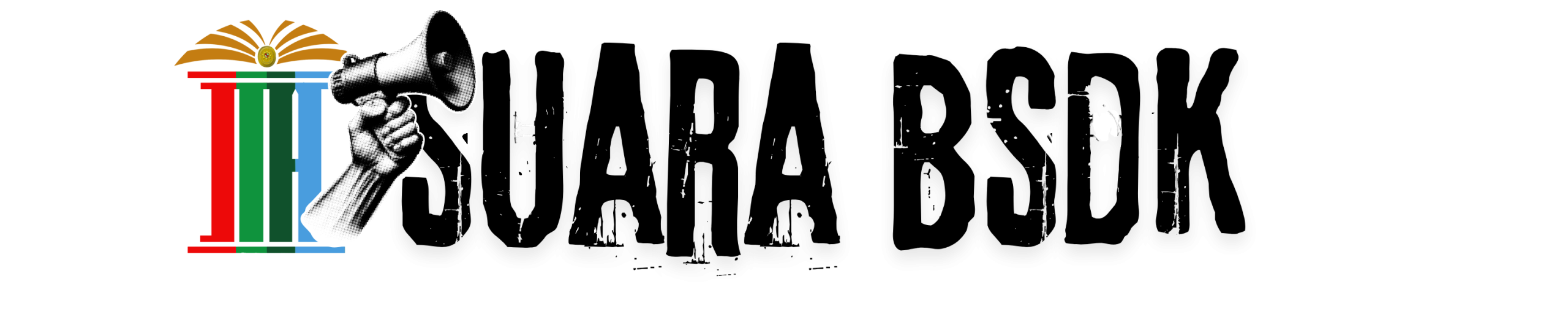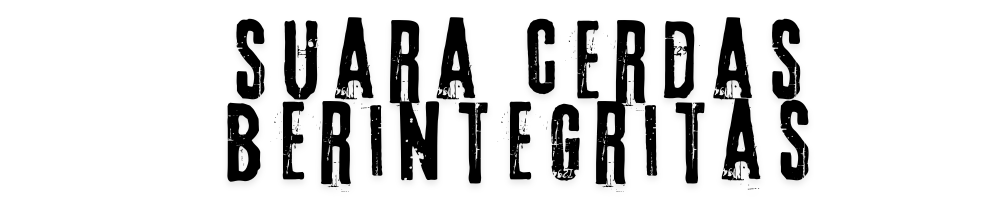Di ufuk utara Nusantara, Pulau Weh berdiri seperti batu karang agung yang sejak abad ke-16 telah dikenal para pelaut dunia. Dari Gujarat hingga Yaman, dari Pegu sampai Eropa, nama pulau kecil ini bergaung sebagai penanda gerbang menuju Selat Malaka, sekaligus sebagai wilayah yang kerap dihindari karena ganasnya ombak dan karang terjal yang mengitari pesisirnya. Para pelaut menyebutnya cantik namun berbahaya; megah namun misterius.
Pada masa itu, Pulau Weh lebih tampak seperti rimba liar: semak belukar tak berujung, binatang- binatang buas berkeliaran, dan di beberapa sudutnya menjadi tempat pembuangan para penjahat dari Kerajaan Aceh. Tak heran jika banyak kapal memilih melintas jauh dari bibir pulau yang tampak sunyi namun menyimpan ancaman.
Beaulieu pernah berkisah betapa rumitnya memasuki Pelabuhan Aceh. Pulau kecil bak benteng alam memagari teluknya, sementara gulungan ombak membuat perjalanan empat mil menuju daratan bisa memakan waktu delapan hari. Gelombang seakan menjadi penjaga yang tak pernah tidur.
Nicolaus de Graaff bahkan dua kali merasakan murka laut di sekitar Pulau Weh. Kapalnya, Dragon, karam ketika ia menuju Malaka pada 1641. Ia selamat bersama awak kapal dengan mendayung perahu kecil menuju Sungai Aceh. Dalam perjalanan berikutnya, pulau itu kembali melemparkan kapal yang ia tumpangi ke daratan dengan badai besar. Ia mengingat pulau itu sebagai tempat penuh babi hutan, kayu bakar yang melimpah, dan para buangan Aceh, sebuah gambaran kasar namun nyata tentang kehidupan di pulau itu pada abad ke-17.
Tak ada catatan pasti apakah kala itu Pulau Weh telah memiliki sistem masyarakat yang teratur. Namun satu hal yang tak membingungkan: babi hutan memang menjadi penghuni setia pulau itu, bahkan hingga kini kerap terlihat berkeliaran di pemukiman penduduk.
Bagi para pelaut dari India, Yaman, dan Gujarat yang menuju Malaka atau Batavia, perairan Pulau Weh adalah persimpangan yang tak terelakkan, namun tetap dihindari. Selain ombak besar dan arus kuat, teluk-teluknya seolah dipagari pulau-pulau kecil yang menyulitkan pendaratan. Muhit, penulis pada tahun 1554, bahkan mewanti-wanti agar pelaut tak mendekati Gamisfalah, nama lama untuk Pulau Weh karena pegunungan Lamuri menjorok ke laut dan arusnya ganas.
Namun justru karena posisinya yang strategis itu, pada abad ke-19 Hindia Belanda menjadikan Pulau Weh sebagai pelabuhan bebas, tempat persinggahan kapal-kapal besar yang mengisi air tawar dan batu bara sebelum melanjutkan pelayaran lintas samudra.
Pada abad ke-17 hingga ke-18, pulau ini diperkirakan masih jarang berpenghuni atau dihuni oleh orang-orang yang diasingkan oleh Kerajaan Aceh pada masa Sultan Ali Riayat Syah Al Qahhar hingga Sultan Iskandar Muda. Di era kejayaannya, kekuasaan Aceh membentang dari Sumatera Barat hingga Malaka, menjadikan Pulau Weh bagian penting dari wilayah kekuasaan kerajaan yang termasyhur itu.
Di masa Sultan Ali Riayat Syah Al Qahhar, Aceh menjadi pusat perdagangan rempah: lada dari Sumatera dan rempah Maluku diekspor ke Laut Merah, menuju karavan-karavan dagang di Mediterania dan Venesia. Aceh pun menjadi rebutan kekuatan besar. Portugis berupaya
menaklukkannya, namun bantuan dari Turki dalam bentuk meriam dan ahli senjata mampu memperkuat pertahanan kerajaan.
Pada tahun 1589, Sultan Ala’ad-Din Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammil naik takhta. Dari garis keturunannya inilah kelak lahir Panglima Pulau Weh: Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Pada masanya, Aceh membuka hubungan dagang dengan Inggris dan Belanda. Lada menjadi magnet yang menarik bangsa-bangsa Eropa, namun juga melahirkan kecurigaan di antara mereka, terutama Belanda yang resah melihat keleluasaan Portugis di Aceh.
Pada 1602, Adipati Maurits dari Belanda mengirim surat penuh diplomasi dan keluh kesah tentang perlakuan Portugis terhadap awak kapalnya. Utusan Belanda disambut di Aceh, dan sebagai balasan, dua tahun kemudian Sultan mengirim utusan terhormat: Abdul Hamid, pria berusia 71 tahun yang akhirnya wafat di Belanda dan dimakamkan dengan hormat di Gereja Sint-Peter, Middleburg.
Dari rangkaian hubungan diplomatik dan kekuasaan yang mengalir dari istana Aceh, akhirnya muncul satu nama penting dalam sejarah Pulau Weh: Panglima Teuku Po Miruk Abdul Wahid, penguasa pulau itu pada masa Sultan Alaidin Mansyur Syah. Ia berasal dari garis keturunan Teuku Bentara Giging, cicit Sultan Ala’ad-Din Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammil.
Riwayat Pulau Weh bukan sekadar kisah pulau kecil di ujung Sumatra. Ia adalah persinggahan para pelaut dunia, saksi gelombang besar kerajaan, pintu gerbang jalur rempah, dan tempat di mana sejarah Aceh menanamkan salah satu akar kekuasaannya.
Pulau Weh adalah tebing masa lalu yang masih berdiri tegak didekap samudra, diselimuti legenda, dan banyak melahirkan para penggawa keadilan di negeri ini.


BSDK MA
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI