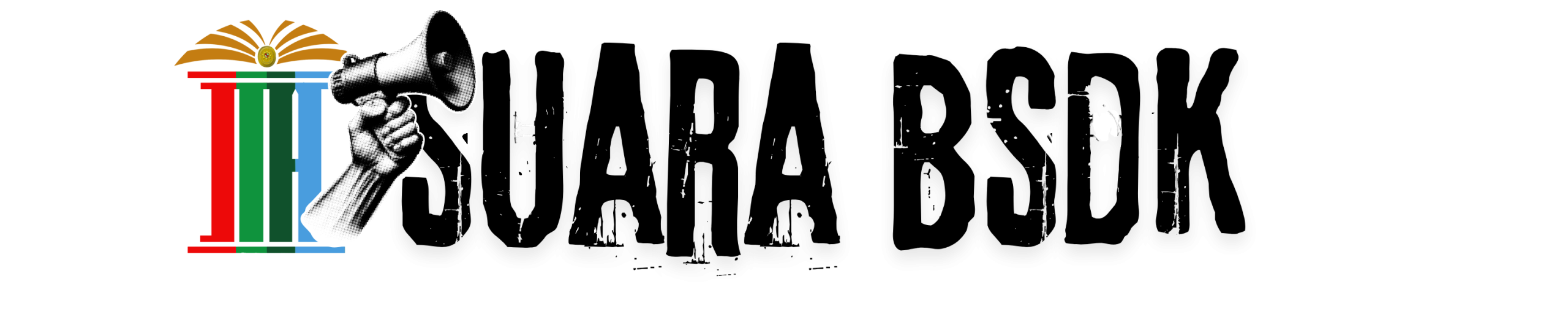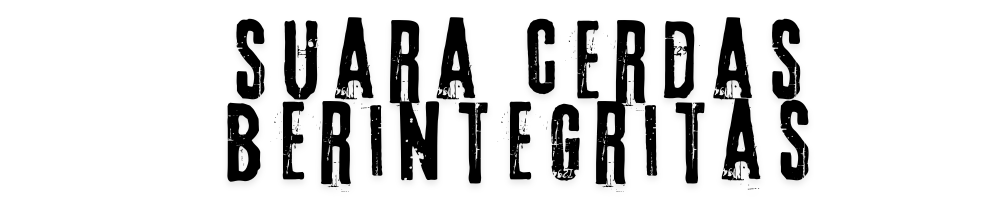Ekstradisi merupakan mekanisme hukum lintas negara yang dirancang untuk menjawab keterbatasan asas teritorial dalam penegakan hukum pidana.[1] Dalam konsepsi klasik hukum pidana, kewenangan negara untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan dibatasi oleh wilayah kedaulatannya. Namun, perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa kejahatan modern tidak lagi mengenal batas negara. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta mobilitas manusia yang tinggi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, seperti korupsi transnasional, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan terorganisasi internasional. Dalam konteks tersebut, ekstradisi menjadi instrumen penting untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi sebagai tempat berlindung (safe haven).[2]
Meskipun memiliki fungsi strategis dalam kerja sama internasional, ekstradisi tidak dapat dipahami sebagai kewajiban absolut yang bersifat otomatis. Setiap permintaan ekstradisi selalu berhadapan dengan sistem hukum nasional negara diminta, khususnya prinsip kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ekstradisi berada dalam ruang tarik-menarik antara kepentingan penegakan hukum internasional dan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak individu yang berada dalam yurisdiksinya. Di sinilah peran kontrol yudisial memperoleh relevansi yang sangat penting.
Kontrol yudisial dalam ekstradisi diwujudkan melalui kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menilai permintaan ekstradisi sebelum dilaksanakan oleh cabang eksekutif. Pemeriksaan ini sering kali melahirkan apa yang disebut sebagai hambatan yudisial, yakni kondisi ketika pengadilan melakukan pengujian hukum secara ketat sehingga proses ekstradisi menjadi panjang atau bahkan berujung pada penolakan. Hambatan yudisial kerap dipersepsikan sebagai penghalang efektivitas kerja sama internasional. Namun, dari perspektif negara hukum, hambatan tersebut justru merupakan konsekuensi logis dari penempatan pengadilan sebagai penjaga terakhir legalitas dan pelindung hak asasi manusia.
Dalam kerangka due process of law, pengadilan tidak dibenarkan menerima permintaan ekstradisi secara serta-merta. Pemeriksaan yudisial mencakup aspek formal, seperti keabsahan dokumen permintaan, kewenangan pejabat yang mengajukan, serta kepastian identitas orang yang dimintakan. Selain itu, pengadilan juga melakukan pengujian aspek materiil yang meliputi pemenuhan asas double criminality, larangan ne bis in idem, ketentuan daluwarsa, serta pengecualian terhadap tindak pidana politik atau militer. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan seseorang dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan melalui prosedur yang adil.
Perbedaan sistem hukum antarnegara semakin memperkuat kompleksitas kontrol yudisial dalam ekstradisi. Dalam tradisi common law, peran pengadilan sangat menonjol melalui mekanisme committal hearing, yaitu tahap pemeriksaan awal untuk menilai apakah bukti yang diajukan negara peminta memenuhi standar prima facie. Meskipun secara teoritis tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan pokok perkara, standar tersebut dalam praktik sering kali mendorong pengadilan melakukan penilaian substansi secara tidak langsung. Akibatnya, proses ekstradisi dapat berkembang menjadi semacam persidangan singkat (mini-trial) yang menyita waktu dan sumber daya, serta berpotensi mengurangi efektivitas kerja sama internasional.
Sebaliknya, negara-negara dengan tradisi civil law cenderung menempatkan ekstradisi dalam kerangka hubungan antar negara yang lebih bersifat administratif-yudisial. Ruang lingkup pemeriksaan pengadilan dibatasi pada pengujian legalitas permintaan dan pemenuhan syarat normatif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional atau perjanjian ekstradisi. Kendati demikian, pembatasan tersebut tidak berarti meniadakan peran pengadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menolak ekstradisi apabila terdapat risiko nyata terjadinya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau proses peradilan yang tidak adil di negara peminta.[3]
Perbedaan pendekatan antara common law dan civil law menunjukkan bahwa hambatan yudisial dalam ekstradisi tidak semata-mata berkaitan dengan teknik prosedural, melainkan juga mencerminkan filosofi hukum dan tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan negara lain. Dalam konteks ini, kontrol yudisial berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara tuntutan efektivitas kerja sama internasional dan kewajiban negara diminta untuk menjaga nilai-nilai fundamental dalam sistem hukumnya.
Dari sudut pandang teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, praktik ekstradisi mencerminkan kecenderungan primat hukum nasional. Prof. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa meskipun ekstradisi bersumber dari perjanjian internasional, pelaksanaannya tetap tunduk pada mekanisme dan prosedur hukum nasional masing-masing negara.[4] Tidak terdapat kewajiban mutlak bagi suatu negara untuk menyerahkan seseorang melalui ekstradisi, kecuali dalam kerangka prinsip aut dedere aut judicare, yang memberikan pilihan antara mengekstradisi atau mengadili sendiri pelaku kejahatan. Dengan demikian, kontrol yudisial yang ketat merupakan ekspresi sah dari kedaulatan hukum nasional yang tetap diakui dalam hukum internasional.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang menempatkan keadilan prosedural sebagai prasyarat legitimasi penegakan hukum. Prof. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi represif, melainkan harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang mengabaikan prosedur justru berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan melahirkan ketidakadilan baru.[5] Dalam konteks ekstradisi, kontrol yudisial berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya penyerahan seseorang ke yurisdiksi yang berpotensi melanggar hak-hak dasarnya.
Dalam sistem hukum Indonesia, peran kontrol yudisial dalam ekstradisi semakin relevan seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pengakuan terhadap tindak pidana lintas batas negara serta menegaskan asas-asas berlakunya hukum pidana di luar wilayah negara.[6] Di sisi lain, arah pembaruan hukum acara pidana menekankan penguatan jaminan hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ini, ekstradisi harus dipahami sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang tunduk pada prinsip due process of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Meski demikian, praktik ekstradisi tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik dan diplomatik. Proses yudisial yang panjang dan kompleks terkadang dimanfaatkan sebagai sarana penundaan atau penolakan terselubung terhadap permintaan ekstradisi. Dalam situasi tertentu, independensi peradilan dijadikan justifikasi formal oleh cabang eksekutif untuk menghindari konsekuensi politik atau diplomatik. Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan yudisial dalam ekstradisi berada di persimpangan antara hukum dan politik, sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap prosesnya.
Sebagai penutup, menurut penulis hambatan yudisial dalam ekstradisi merupakan refleksi dari ketegangan inheren antara efektivitas penegakan hukum internasional dan prinsip kedaulatan hukum nasional serta keadilan prosedural. Kontrol yudisial menegaskan bahwa kerja sama internasional di bidang pidana tidak dapat dijalankan dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukanlah menghilangkan kontrol yudisial, melainkan merancang mekanisme ekstradisi yang proporsional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi efektivitas kerja sama internasional, sejalan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh komunitas global.[7]
Referensi
[1] Geoff Gilbert, Transnational Fugitive Offenders in International Law (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), hlm. 3–5.
[2] I.A. Shearer, Extradition in International Law (Manchester: Manchester University Press, 1971), hlm. 12–18.
[3] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 130–136.
[4] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 85–90.
[5] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 39–42.
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Extradition (Vienna: United Nations, 2004), hlm. 9–14.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI